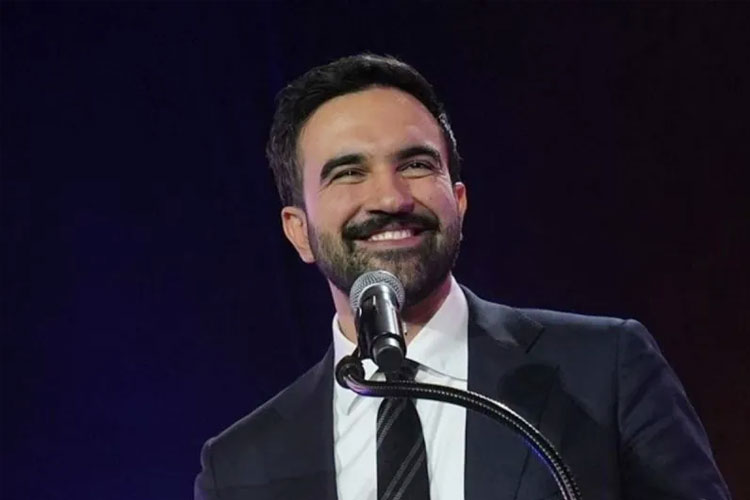TIMES MALANG, MALANG – Indonesia kembali dihadapkan pada kenyataan yang menyentil logika pembangunan manusianya. Setiap tahun, lebih dari 1,3 juta lulusan sarjana baru dilepas ke pasar kerja.
Di sisi lain, data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga kerja baru hanya sekitar 300 ribu per tahun. Artinya, ada sekitar sejuta orang berpendidikan tinggi yang langsung berhadapan dengan pengangguran sesaat setelah wisuda.
Kesenjangan ini bukan sekadar statistik. Ia adalah potret dari kemiskinan yang berubah wujud bukan lagi karena tidak sekolah, melainkan karena pendidikan tidak menjamin kehidupan yang layak.
Dalam masyarakat yang meyakini pendidikan sebagai tangga sosial, kenyataan ini terasa seperti tamparan keras: ternyata, ijazah tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan.
Masalah ini bukan soal jumlah semata, melainkan soal arah. Selama ini, kebijakan pendidikan kita cenderung mengejar kuantitas, bukan relevansi. Universitas mencetak lulusan sebanyak mungkin, tapi dunia kerja tidak berubah secepat itu.
Di ruang kelas, mahasiswa sibuk mengejar nilai; sementara di lapangan, industri menuntut keterampilan baru yang bahkan belum pernah diajarkan di kampus. Akibatnya, lahirlah generasi sarjana yang cerdas di atas kertas, tapi kehilangan daya guna di lapangan.
Fenomena ini sering disebut sebagai educated unemployment pengangguran berpendidikan. Sebuah paradoks yang unik bagi negara berkembang: semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula risiko menganggur.
Bagi Indonesia, ini bukan sekadar ironi, tapi alarm keras bahwa sistem ekonomi dan pendidikan sedang berjalan di dua jalur yang tak pernah berpotongan.
Di satu sisi, pemerintah bangga dengan peningkatan angka partisipasi kuliah. Tapi di sisi lain, tidak ada strategi matang untuk menyerap hasilnya ke dunia kerja. Padahal, pasar tenaga kerja modern menuntut kemampuan adaptif, kreativitas, dan kompetensi teknis yang relevan dengan industri digital, energi hijau, dan sektor berbasis data. Sementara itu, kurikulum di banyak perguruan tinggi masih berorientasi pada teori dan hafalan, bukan inovasi dan praktik.
Kondisi ini melahirkan apa yang bisa disebut sebagai kemiskinan intelektual: orang berpendidikan tapi tidak berdaya secara ekonomi. Ia bukan miskin karena malas, tapi karena sistem tidak menyediakan ruang bagi pengetahuan untuk menjadi kekuatan ekonomi.
Bayangkan, lulusan teknik bekerja di ojek daring, sarjana ekonomi membuka warung kopi, atau lulusan hukum menjadi admin media sosial. Semua itu bukan cermin kegagalan individu, melainkan kegagalan struktur dalam menciptakan ekosistem kerja yang adil.
Kemiskinan hari ini tidak selalu lahir dari ketidaktahuan, melainkan dari ketimpangan antara kapasitas manusia dan ketersediaan kesempatan. Dan ketimpangan itu bersumber dari lemahnya koordinasi antara dunia pendidikan, industri, dan kebijakan negara.
Jika kita menengok negara-negara maju, mereka justru menempatkan pendidikan sebagai bagian integral dari strategi ekonomi nasional. Setiap jurusan yang dibuka di universitas disusun berdasarkan proyeksi kebutuhan pasar 5 hingga 10 tahun ke depan.
Ada jembatan yang kuat antara kampus dan industri, antara ruang kuliah dan ruang produksi. Sementara di Indonesia, sebagian besar lulusan masih harus berjalan sendiri mencari arah.
Situasi ini berpotensi menjadi bom waktu sosial. Ketika jutaan sarjana menganggur, yang muncul bukan hanya kekecewaan personal, tapi juga frustrasi kolektif. Mereka yang menginvestasikan waktu dan biaya untuk pendidikan, akan merasa sistem ini tidak adil. Dalam jangka panjang, ini bisa melahirkan generasi skeptis terhadap nilai pendidikan itu sendiri.
Padahal, di saat yang sama, banyak sektor ekonomi kita masih kekurangan tenaga ahli. Pertanian modern, energi terbarukan, bioteknologi, riset kelautan, bahkan manajemen data semua membutuhkan tenaga kerja terampil. Tapi karena tidak ada peta jalan yang jelas antara pendidikan dan kebutuhan industri, peluang itu berlalu begitu saja.
Maka, yang kita butuhkan bukan hanya mencetak sarjana, tapi mendesain ulang ekosistem ketenagakerjaan nasional. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan berbasis proyeksi data tenaga kerja.
Perguruan tinggi harus mulai merumuskan ulang kurikulum berbasis kompetensi masa depan, bukan sekadar mengikuti tren masa lalu. Dunia industri pun harus lebih terbuka membangun kemitraan dengan kampus, memberikan ruang magang, riset terapan, dan inovasi produk bersama.
Lebih dari itu, kita perlu menggeser orientasi sosial dari “mencari kerja” menjadi “mencipta kerja”. Paradigma kewirausahaan harus ditanamkan sejak dini sebagai bagian dari pendidikan karakter. Kampus tidak lagi boleh hanya menjadi pabrik ijazah, tapi juga inkubator ide dan inovasi.
Kemiskinan di Indonesia hari ini bukan lagi semata-mata soal penghasilan rendah, tapi soal ketidaksanggupan sistem untuk menghubungkan ilmu dengan kesejahteraan. Kita punya sumber daya manusia yang besar, tapi gagal mengelolanya menjadi kekuatan ekonomi yang produktif.
Selama kebutuhan kerja hanya 300 ribu, sementara lulusan sarjana 1,3 juta, maka jurang pengangguran intelektual akan terus menganga. Dan selama negara masih mengukur keberhasilan pendidikan dari jumlah lulusan, bukan dari kebermanfaatannya, maka kemiskinan akan tetap menemukan bentuk barunya bahkan di tengah gedung-gedung kampus yang megah.
Pendidikan semestinya menjadi jembatan menuju kehidupan yang lebih baik. Tapi di Indonesia, jembatan itu kini terasa menggantung di udara kokoh di ujung teori, tapi belum menyentuh tanah realitas. (*)
***
*) Oleh : Iswan Tunggal Nogroho, Praktisi Pendidikan.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |