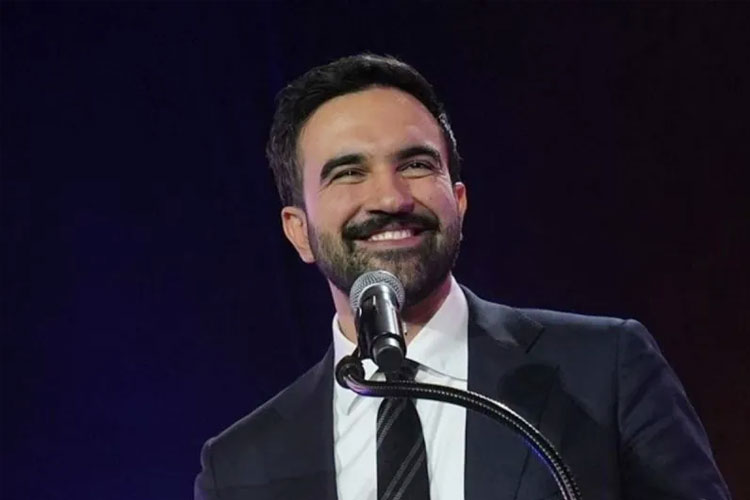TIMES MALANG, MALANG – Setiap kali pemerintah meluncurkan kebijakan baru, kita selalu dihadapkan pada satu pertanyaan sederhana namun mendasar: untuk siapa kebijakan itu dibuat?
Sayangnya, jawaban yang paling jujur seringkali pahit kebijakan publik di negeri ini kerap lahir tanpa benar-benar mendengar publik. Ia disusun di ruang rapat yang steril dari kenyataan lapangan, dibahas dalam bahasa teknokratis yang jauh dari jangkauan rakyat, lalu diumumkan sebagai “keputusan terbaik” atas nama kepentingan bersama.
Inilah paradoks kebijakan publik di Indonesia: dibuat atas nama rakyat, tapi sering kali tidak berpihak kepada rakyat. Di atas kertas, hampir semua kebijakan terlihat indah penuh visi, sasaran, dan target pembangunan. Namun di lapangan, kebijakan itu sering berubah menjadi beban baru bagi masyarakat yang justru menjadi alasan keberadaannya.
Contohnya mudah kita temui. Dari kebijakan subsidi yang salah sasaran, proyek infrastruktur yang menggusur ruang hidup warga, sampai reformasi pendidikan yang sibuk mengganti kurikulum tanpa menyentuh akar persoalan kualitas guru. Semua menunjukkan gejala yang sama: pemerintah lebih cepat membuat keputusan daripada mendengarkan suara masyarakat.
Kebijakan publik sejatinya adalah wujud dari kontrak sosial antara negara dan warganya. Ia seharusnya berangkat dari kebutuhan, aspirasi, dan harapan rakyat, bukan sekadar dari logika efisiensi atau tekanan ekonomi global.
Tapi yang terjadi, logika kebijakan publik kita cenderung elitis berpihak pada data statistik, bukan pada rasa manusia. Rakyat sering diperlakukan hanya sebagai objek kebijakan, bukan subjek yang punya hak untuk didengar.
Masalahnya, banyak kebijakan yang tidak lahir dari proses partisipatif. Rancangan peraturan disusun terburu-buru, uji publik sekadar formalitas, dan evaluasi sering tidak dilakukan secara terbuka. Padahal, tanpa partisipasi masyarakat, kebijakan publik kehilangan legitimasi moralnya. Ia mungkin sah secara hukum, tapi rapuh secara sosial.
Kita masih ingat polemik Omnibus Law yang disahkan dengan kecepatan luar biasa, atau kenaikan harga BBM yang dilakukan tanpa dialog yang memadai. Pemerintah berdalih semua demi efisiensi fiskal dan daya saing ekonomi.
Di lapangan, rakyat menanggung beban sosialnya: harga naik, daya beli turun, dan kemiskinan baru bermunculan. Yang lebih ironis, ketika publik bereaksi, justru publik pula yang dianggap “tidak memahami kebijakan”.
Di sinilah pentingnya politik empati dalam perumusan kebijakan publik. Empati bukan kelemahan, melainkan kecerdasan moral negara dalam memahami realitas sosial warganya. Negara tidak boleh hanya hadir ketika memberi perintah atau menegakkan aturan, tapi juga harus hadir ketika masyarakat merasa kehilangan arah dan harapan.
Kebijakan publik yang efektif bukan yang sekadar “berhasil di neraca”, melainkan yang mengembalikan rasa percaya antara rakyat dan negara. Dan rasa percaya itu hanya tumbuh ketika kebijakan lahir dari dialog, bukan monolog kekuasaan.
Ironisnya, proses kebijakan di Indonesia sering berhenti di tahap pengumuman, bukan pengawasan. Setelah kebijakan diluncurkan dengan seremoni besar, tak banyak yang dilakukan untuk menilai apakah implementasinya berjalan sesuai harapan. Akibatnya, banyak kebijakan yang berakhir di tengah jalan menguap tanpa evaluasi, padahal anggaran sudah habis.
Kelemahan lain yang tak kalah penting adalah ketergantungan kita pada paradigma jangka pendek. Banyak kebijakan dibuat hanya untuk kepentingan elektoral, bukan keberlanjutan pembangunan.
Proyek jalan, bansos, atau program digitalisasi sering muncul menjelang tahun politik, seolah pembangunan hanya penting ketika ada pemilu. Padahal, kebijakan publik sejati mestinya berpijak pada visi jangka panjang, bukan sekadar siklus kekuasaan lima tahunan.
Kita perlu mengingat kembali bahwa kebijakan publik bukan sekadar dokumen, melainkan alat untuk memperbaiki kualitas hidup manusia. Jika kebijakan hanya melayani kepentingan birokrasi, maka ia akan kehilangan rohnya sebagai instrumen keadilan sosial.
Kebijakan yang baik bukan yang “populer di media”, tapi yang mampu menembus kesenjangan dan mengurangi ketimpangan.
Karena itu, reformasi kebijakan publik harus dimulai dari perubahan cara pandang pemerintah terhadap rakyat. Rakyat bukan beban, melainkan mitra pembangunan. Setiap kebijakan harus lahir dari riset sosial yang mendalam, konsultasi publik yang terbuka, dan keberanian untuk mengevaluasi diri. Tidak ada kebijakan yang sempurna, tapi setiap kebijakan harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan mereka yang terdampak.
Kritik terhadap kebijakan publik bukan tanda kebencian terhadap pemerintah, tapi tanda cinta terhadap republik. Karena tanpa kritik, negara bisa kehilangan arah. Demokrasi bukan tentang seberapa banyak keputusan dibuat, tapi seberapa dalam keputusan itu mewakili suara yang terdampak.
Kita tentu ingin negara ini maju. Tapi kemajuan tidak akan berarti jika hanya bisa dirasakan oleh segelintir orang. Kebijakan publik yang baik harus menurunkan jarak antara pusat dan pinggiran, antara yang berkuasa dan yang diperintah.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan kebijakan publik bukan pada berapa miliar anggaran yang diserap, tapi pada seberapa banyak rakyat yang hidupnya membaik karenanya.
Selama kebijakan publik masih dibuat tanpa publik, maka yang akan tumbuh hanyalah ketidakpercayaan. Dan tanpa kepercayaan, tidak ada pembangunan yang akan benar-benar berhasil. Karena negara kuat bukan karena banyaknya aturan, tapi karena keadilan yang dirasakan oleh rakyatnya. (*)
***
*) Oleh : Moh. Farhan Aziz, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DPD LIRA Kota Malang.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |