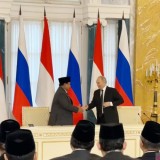TIMES MALANG, TANGERANG – Presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden yakni syarat minimal dukungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini dimulai lewat UU No. 23 Tahun 2003, menetapkan ambang batas 15% kursi DPR atau 20% suara sah nasional. Kemudian dinaikkan menjadi 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional lewat UU No. 42 Tahun 2008. Ketentuan ini dipertahankan pada UU No. 7 Tahun 2017.
Pendukung threshold menganggap kebijakan ini memperkuat sistem presidensial dan stabilitas pemerintahan. Meski, penentangnya menganggap threshold membatasi hak partai untuk mengajukan calon presiden.
Para pendukungnya menilai threshold tak relevan dalam pemilu serentak, bahkan membatasi pilihan rakyat. Partai kecil terpaksa berkoalisi dengan partai besar, membuat polarisasi politik. Pilpres 2019, semisal, justru menghadirkan dua pasangan calon.
Efektifnya threshold dalam membuat stabilitas pemerintahan masih jadi polemik. Pemerintahan hasil Pilpres 2004-2014 relatif stabil, tetapi dipengaruhi faktor-faktor lain, seperti kemampuan presiden merangkul oposisi. Koalisi besar pendukung pemerintah pada periode pasca 2019 membikin kegaduhan melemahnya fungsi checks and balances.
Parliamentary Threshold
Parliamentary threshold atau ambang batas parlemen ialah syarat minimal suara nasional yang mesti dicapai partai politik untuk mendapat kursi di parlemen. Mulanya, kebijakan ini dimulai pada Pemilu 2009 dengan ambang batas 2,5%, naik menjadi 3,5% pada Pemilu 2014, dan 4% pada Pemilu 2019.
Pendukung threshold mengklaim bahwa ambang batas yang tinggi menyederhanakan sistem kepartaian dan meningkatkan efisiensi parlemen. Walau, kritik menyebut bahwa kebijakan ini menghilangkan keterwakilan kelompok minoritas.
Threshold berimbas pada lanskap politik Indonesia. Jumlah partai di parlemen menyusut dari 16 partai pada Pemilu 2004 menjadi 9 partai pada Pemilu 2019. Hal ini meningkatkan efisiensi parlemen tetapi memicu keresahan atas keterwakilan rakyat. Perbandingan dengan negara lain menunjukkan variasi penerapan threshold, seperti 5% di Jerman, 10% di Turki, atau hanya 0,67% di Belanda.
Efek samping dari threshold yakni banyak suara yang terbuang. Pada Pemilu 2019, sekitar 6 juta suara (5,32% dari total suara sah) tidak terkonversi menjadi kursi sebab partainya tidak lolos threshold. Kondisi ini merangsang pertanyaan terkait prinsip "one man, one vote" dalam demokrasi.
Pemilihan Langsung vs Tidak Langsung
Indonesia awalnya menggunakan sistem pemilihan tidak langsung, di mana presiden dipilih oleh parlemen. Perubahan besar terjadi pada 2004 dengan diterapkannya pemilihan langsung. Sistem ini dianggap lebih demokratis karena memberi kedaulatan penuh kepada rakyat.
Kendati demikian, sistem ini dikritik karena ongkosnya yang tinggi dan risiko politik uang. Pemilihan langsung telah meningkatkan partisipasi politik rakyat, walau belum bebas dari masalah seperti biaya kampanye mahal dan konflik horizontal.
Sebaliknya, pemilihan tidak langsung dianggap lebih hemat dan efisien, kendati condong membuka peluang politik transaksional antara calon dan anggota DPRD. Survei LSI pada 2014 silam menunjukkan 84,1% masyarakat mendukung pemilihan langsung.
Evaluasi Sistem Pemilu
Sistem pemilu serentak pada 2019 tujuannya kala itu menyelaraskan kekuatan eksekutif dan legislatif. Meski demikian, pelaksanaannya membikin berbagai persoalan teknis.
Penerapan ambang batas parlemen 4% juga membuat sekitar 15,6 juta suara terancam "terbuang" pada Pemilu 2024. Optimalisasi teknologi, pendidikan politik, dan revisi parliamentary threshold menjadi rekomendasi utama untuk perbaikan sistem pemilu kedepannya.
Mahkamah Konstitusi (MK) sudah beberapa kali memutuskan soal threshold dan sistem pemilu. Presidential threshold dinilai sejalan dengan penguatan sistem presidensial meski “panen” kritik karena membatasi hak konstitusional partai. Untuk parliamentary threshold, MK memerintahkan evaluasi besaran 4% berdasarkan kajian ilmiah.
MK juga menyebut sistem pemilu adalah bagian dari open legal policy, memberi ruang bagi pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan sistem sesuai dinamika politik. Pasalnya, terlalu banyak perubahan sistem bisa menimbulkan ketidakpastian hukum.
***
*) Oleh : Heru Wahyudi, Dosen di Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Pamulang.
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |