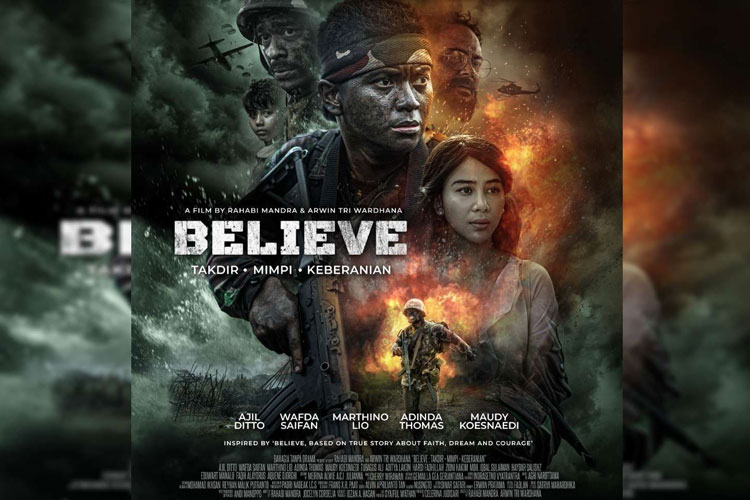TIMES MALANG, JAKARTA – Setiap 1 Mei, dunia memperingati Hari Buruh sebagai simbol perjuangan kelas pekerja atas hak, martabat, dan kesejahteraan. Di Indonesia, peringatan ini kerap diwarnai demonstrasi, spanduk, dan orasi di jalan-jalan. Namun di balik kemeriahan simbolik itu, muncul pertanyaan besar: apakah nasib buruh di negeri ini benar-benar berubah?
Buruh bukan sekadar angka statistik dalam neraca ekonomi. Mereka adalah denyut kehidupan industri, jasa, dan bahkan pemerintahan. Tanpa buruh, tidak ada produk yang lahir, tidak ada pelayanan yang berjalan. Tapi ironisnya, buruh sering menjadi kelompok paling rentan—upah rendah, jam kerja panjang, dan perlindungan yang lemah.
Selama bertahun-tahun, isu utama kaum buruh tetap sama: upah layak, jaminan sosial, dan status kerja yang jelas. UU Cipta Kerja, misalnya, justru memperburuk kekhawatiran buruh karena dianggap lebih berpihak pada investor daripada pekerja. Fleksibilitas tenaga kerja yang dijanjikan kerap diterjemahkan menjadi ketidakpastian kerja.
Digitalisasi juga menghadirkan tantangan baru. Buruh di sektor informal seperti ojek daring kini berada di area abu-abu: bekerja penuh waktu tapi tanpa jaminan seperti pekerja formal. Mereka tidak dianggap karyawan, tapi juga bukan mitra sejati. Hubungan kerja yang cair ini menjadi jebakan baru dalam dunia kerja modern.
Belum lagi persoalan buruh perempuan yang kerap menghadapi diskriminasi, beban ganda, hingga kekerasan di tempat kerja. Perlindungan hukum bagi mereka masih lemah, dan suara mereka sering tenggelam dalam dominasi isu buruh laki-laki.
Di sisi lain, serikat buruh menghadapi tantangan legitimasi. Tidak semua buruh terorganisir, dan sebagian bahkan merasa serikat tidak benar-benar mewakili aspirasi mereka. Padahal kekuatan kolektif adalah kunci untuk menekan kebijakan yang lebih adil dan berpihak.
Negara memiliki peran penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang sehat. Regulasi yang adil, penegakan hukum yang tegas, dan kebijakan ekonomi yang pro-pekerja harus menjadi prioritas. Namun kenyataannya, buruh sering kali hanya dijadikan alat politik musiman.
Masyarakat pun tidak boleh abai. Kita menikmati hasil kerja buruh setiap hari-dari makanan, transportasi, layanan publik, hingga teknologi. Sudah waktunya kita berhenti memandang buruh sebagai "kelas bawah" dan mulai menghargai mereka sebagai pilar utama kehidupan modern.
Peringatan Hari Buruh semestinya menjadi momentum evaluasi, bukan sekadar seremoni. Sudahkah kita memberikan pengakuan yang layak kepada mereka yang membuat roda ekonomi terus berputar?
Jika kesejahteraan buruh terus diabaikan, maka jurang ketimpangan akan makin melebar. Ketimpangan ini bukan hanya ancaman sosial, tapi juga ancaman bagi stabilitas dan kemanusiaan itu sendiri.
Hari Buruh bukan tentang masa lalu yang heroik, tetapi tentang masa depan yang harus diperjuangkan bersama. Ini tentang keadilan kerja, martabat manusia, dan harapan bahwa siapa pun yang bekerja keras layak hidup sejahtera.
Mari kita rayakan Hari Buruh bukan hanya dengan spanduk dan pidato, tapi dengan aksi nyata: mendengarkan, memahami, dan memperjuangkan hak-hak buruh agar tidak lagi menjadi janji yang terus tertunda.
***
*) Oleh : Abdullah Fakih Hilmi AH, S.AP., Akademisi dan Wirausahawan.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |