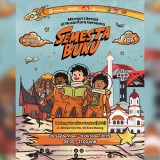TIMES MALANG, MALANG – Di tengah gegap gempita pembangunan nasional, desa kerap diperlakukan sebatas halaman belakang: sunyi, sederhana, dan seolah hanya menunggu kemurahan tangan pusat. Padahal, desa bukanlah ruang kosong. Ia adalah rahim peradaban, tempat lahirnya kebudayaan, kearifan, dan kehidupan yang memberi napas bagi bangsa.
Maka, pembangunan desa yang sejati adalah pembangunan berkeadaban pembangunan yang berakar pada potensi lokal, bukan sekadar impor kebijakan dari meja rapat kota.
Pembangunan berkeadaban berarti menempatkan manusia desa sebagai subjek, bukan objek. Bukan sekadar penerima bantuan, melainkan penggerak yang merawat tanah, budaya, dan tradisinya.
Desa adalah miniatur kemandirian bangsa. Ia punya sawah yang menghidupi, laut yang melimpahkan ikan, hutan yang menyimpan sumber daya, juga kearifan sosial yang menjaga harmoni.
Sayangnya, potensi ini sering tergerus oleh logika pembangunan top-down yang seragam, seolah desa di Papua sama dengan desa di Jawa, atau desa pesisir sama dengan desa pegunungan.
Pembangunan desa berbasis potensi lokal menuntut kesadaran bahwa setiap desa memiliki “DNA” sendiri. Ada desa dengan kekuatan agraris, ada yang kaya laut, ada pula yang menyimpan pusaka budaya.
Jika pembangunan hanya datang dalam bentuk proyek fisik yang seragam pavingisasi jalan, gapura monumental, atau bangunan balai desa maka ruh desa kian pudar. Potensi lokalnya terkubur oleh beton dan birokrasi.
Sebagai contoh, desa pesisir semestinya diperkaya dengan teknologi pengolahan hasil laut, akses pasar bagi nelayan, dan program konservasi ekologi pantai. Desa agraris perlu difasilitasi dengan inovasi pertanian, kemandirian pupuk, serta sistem distribusi hasil panen yang adil.
Sementara desa wisata budaya bisa menghidupkan seni pertunjukan, kuliner khas, dan arsitektur tradisional sebagai magnet ekonomi sekaligus benteng identitas.
Menghormati tradisi berarti mengakui bahwa gotong royong, musyawarah, dan nilai religius adalah modal sosial desa yang tak ternilai. Pembangunan berkeadaban tidak boleh meruntuhkan tatanan ini, melainkan memperkuatnya. Jalan beraspal mulus tak ada artinya bila relasi sosial hancur dan generasi muda tercerabut dari akar tradisinya.
Sayangnya, praktik pembangunan desa masih sering terjebak pada pola lama: proyek berbasis anggaran, bukan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Dana Desa yang mengalir tiap tahun tidak jarang dipakai untuk proyek fisik yang instan, tapi minim manfaat jangka panjang. Desa berlomba mempercantik wajahnya dengan gapura dan plakat, namun lupa menyemai pengetahuan, keterampilan, dan ekonomi rakyat.
Pola seperti ini jelas tidak berkeadaban. Ia melahirkan ketergantungan baru: desa yang tampak megah di luar, tapi rapuh di dalam. Lebih ironis lagi, sebagian aparatur desa terjebak pada politik anggaran yang rawan penyalahgunaan, sehingga potensi lokal hanya jadi jargon di atas kertas.
Kritik ini bukan untuk merendahkan kerja keras pemerintah desa, melainkan sebagai pengingat: pembangunan tidak boleh kehilangan ruh. Desa bukan sekadar ruang administratif, tetapi ruang hidup manusia dengan segala kompleksitas sosial, budaya, dan alamnya.
Desa sebagai Titik Balik Bangsa
Desa berkeadaban berbasis potensi lokal sejatinya adalah kunci untuk membalik wajah pembangunan nasional. Dari desa yang kuat, lahir bangsa yang berdaulat.
Bila petani desa makmur, Indonesia tidak akan bergantung pada impor pangan. Bila nelayan desa sejahtera, kedaulatan laut akan nyata. Bila budaya desa hidup, bangsa ini akan punya jati diri yang kokoh menghadapi gempuran globalisasi.
Di sinilah urgensi pembangunan berbasis potensi lokal: ia menjadikan desa sebagai pusat inovasi, bukan sekadar penerima sisa pembangunan kota. Desa bukan pelengkap, tetapi poros peradaban.
Pembangunan desa berkeadaban membutuhkan kesungguhan politik dan komitmen moral. Pemerintah harus hadir bukan sebagai patron, melainkan mitra. Pendampingan desa sebaiknya berfokus pada pemberdayaan masyarakat, bukan hanya laporan administrasi.
Perguruan tinggi dapat menjadi sahabat desa dengan riset terapan, teknologi tepat guna, dan pendidikan berbasis masyarakat. Sementara generasi muda desa perlu diberi ruang untuk berkreasi, agar tidak terus-menerus eksodus ke kota.
Bayangkan bila setiap desa diberi ruang untuk mengelola potensinya sendiri, dengan dukungan kebijakan yang adil dan akses teknologi yang memadai. Desa pegunungan akan menjadi lumbung pangan organik. Desa pesisir menjadi pusat perikanan berkelanjutan. Desa budaya menjadi destinasi wisata yang menawan tanpa kehilangan jiwanya. Inilah wajah pembangunan berkeadaban yang sesungguhnya: membumi, memanusiakan, dan berakar.
Pembangunan desa berkeadaban berbasis potensi lokal bukan sekadar wacana indah. Ia adalah kebutuhan mendesak jika bangsa ini ingin berdiri di atas kakinya sendiri. Desa tidak boleh terus-menerus jadi halaman belakang yang dilupakan, sementara kota dijadikan panggung utama. Desa adalah sumber, akar, sekaligus masa depan.
Maka, pembangunan desa harus berpijak pada tiga hal: menghidupkan potensi, menghormati tradisi, dan menyejahterakan manusia. Tanpa itu, pembangunan hanya akan menjadi bangunan tanpa jiwa. Dengan itu, desa akan menjadi pusat peradaban tempat lahirnya kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan yang sejati.
***
*) Oleh: Abdul Aziz, S.Pd., Praktisi Pendidikan.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |