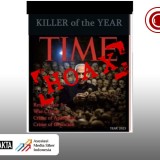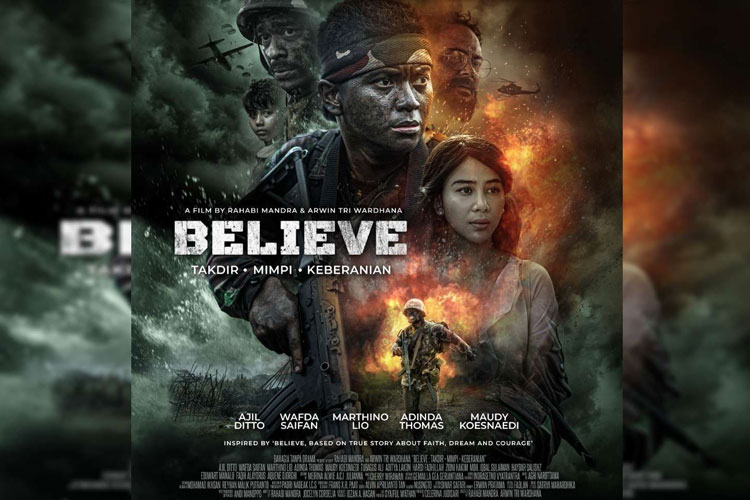TIMES MALANG, BANYUWANGI – Pendidikan barak militer merupakan model pendidikan yang menekankan pada kedisiplinan tinggi, struktur hierarkis, serta pelatihan fisik dan mental yang intensif. Model ini di cetuskan dan di praktikkan oleh gubernur Jawa Barat (KDM) sebagai upaya penanganan anak bermasalah di sekolah. Sehingga, model ini banyak di bicarakan dalam konteks pembentukan karakter dan wacana revitalisasi sistem pendidikan nasional.
Namun, pendekatan ini tidak lepas dari pro dan kontra, baik dari perspektif pedagogi, psikologi perkembangan, hingga teori sosial politik.
Pendukung pendidikan barak militer menilai bahwa sistem ini dapat memperkuat karakter siswa melalui disiplin dan tanggung jawab. Teori pendidikan karakter dari Thomas Lickona dalam bukunya Educating for Character (1991) menyatakan bahwa pendidikan harus menanamkan nilai moral seperti tanggung jawab, respek, dan kewarganegaraan.
Pendidikan barak militer dinilai relevan dengan gagasan ini, karena secara sistematis membentuk perilaku yang patuh terhadap aturan dan tangguh menghadapi tekanan.
Dalam konteks pembentukan identitas nasional, Durkheim dalam Education and Sociology (1956) menekankan bahwa pendidikan memiliki fungsi sosial untuk mentransmisikan nilai-nilai kolektif kepada generasi muda.
Pendidikan militer dianggap mampu memperkuat solidaritas dan loyalitas terhadap negara, terutama di tengah arus globalisasi yang kerap mengikis rasa kebangsaan.
Selain itu, pendidikan barak juga diyakini mampu meredam kenakalan remaja. B.F. Skinner dalam teori behaviorism-nya menyatakan bahwa perilaku dapat dibentuk melalui penguatan positif dan negatif (Skinner, Science and Human Behavior, 1953). Sistem militer yang berbasis pada reward dan punishment memberikan ruang untuk mengontrol perilaku siswa secara lebih ketat.
Meski demikian, pendekatan barak militer juga menuai kritik dari para ahli pendidikan dan psikologi, beberapa ahli meyakini model pendidikan seperti ini akan menciptakan represi psikologis dan minimnya ruang kritis.
Jean Piaget, dalam teorinya tentang perkembangan kognitif (The Moral Judgment of the Child, 1932), menyatakan bahwa anak dan remaja membutuhkan ruang untuk mengembangkan otonomi moral melalui interaksi sosial, bukan semata ketaatan pada otoritas. Pendidikan militer yang terlalu menekankan kepatuhan dapat menghambat perkembangan moral dan logika anak.
Demikian pula, menurut Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed (1970), pendidikan yang represif menciptakan relasi vertikal antara guru dan murid, menjadikan murid sebagai objek yang harus menerima perintah tanpa dialog. Pendidikan barak militer, dalam kerangka ini, berpotensi menciptakan apa yang disebut Freire sebagai “banking education” model pendidikan satu arah yang anti-kritik.
Dari perspektif psikologi perkembangan, Erik Erikson menekankan pentingnya fase pencarian jati diri pada masa remaja (Childhood and Society, 1950). Pemaksaan struktur yang kaku dapat menimbulkan konflik identitas dan perlawanan psikologis. Bahkan, sejumlah riset menunjukkan bahwa sistem pendidikan yang keras berisiko menimbulkan trauma, kecemasan, dan gangguan adaptasi sosial.
Dengan demikian, jika di refleksikan secara teoritikal, model pendidikan seperti ini memiliki nilai strategis dan energik nya masing-masing. Melalui beberapa pendekatan teori para ahli baik secara tekstual maupun kontekstual dapat di simpulkan bahwa penerapan pendidikan barak militer sebaiknya tidak dilakukan secara penuh, melainkan melalui pendekatan integratif dan adaptif.
Nilai-nilai positif dari dunia militer seperti disiplin, kerja sama tim, dan kepemimpinan dapat disisipkan dalam kurikulum pendidikan umum melalui metode yang dialogis dan humanistik. Pendidikan bukan sekadar alat pembentuk warga yang patuh, tetapi ruang tumbuh bagi manusia yang bebas, berpikir, dan bertanggung jawab secara sosial.
***
*) Oleh : Ilham Layli Mursidi, Ketua Umum HMI Cabang Banyuwangi.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |