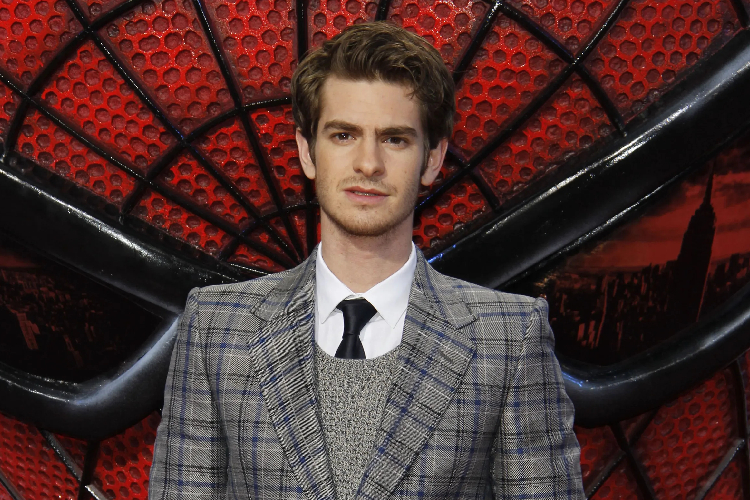TIMES MALANG, JAKARTA – Saat berbincang santai dengan para petani di Majalengka, Jawa Barat, Senin (7/4/2025), Presiden Prabowo Subianto melontarkan candaan: “banyak orang pintar justru tidak menjadi apa-apa”.
Pernyataan ini menggambarkan realitas yang kerap kita temui dalam kehidupan sehari-hari: banyak orang dengan kecerdasan intelektual tinggi justru tidak mampu meraih kesuksesan dalam bidangnya, sebaliknya mereka yang secara akademik biasa-biasa saja justru mampu melesat jauh dan menjadi tokoh penting.
Statement Prabowo di atas, selaras dengan pendapat Goleman, seorang psikolog dan penulis Amerika yang dikenal karena karyanya tentang kecerdasan emosional.
Dalam bukunya berjudul “Emotional Intelligence” (1995), Goleman mengungkapkan bahwa kecerdasan emosional berperan jauh lebih besar dalam menentukan kesuksesan hidup dan karier seseorang dibandingkan dengan kecerdasan intelektual.
Kecerdasan intelektual hanya menyumbang sekitar 20% terhadap kesuksesan seseorang. Sisanya, sekitar 80%, ditentukan oleh faktor-faktor lain, terutama kecerdasan emosional.
Ini menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan seseorang. Ada faktor lain yang sering luput dari perhatian, namun justru menentukan sejauh mana seseorang mampu meraih kesuksesan baik dalam karier maupun kehidupan sosial. Menurut Daniel Goleman, aspek penting itu adalah “kecerdasan emosional.”
Kecerdasan Emosional
Kita sering mendengar istilah "pintar secara emosional," tapi apa sebenarnya maksudnya? Kecerdasan emosional atau emotional intelligence (EQ) adalah kemampuan seseorang untuk mengenali dan mengelola emosinya sendiri, serta memahami dan merespons emosi orang lain dengan bijak.
Konsep ini menjadi populer sejak diperkenalkan oleh Daniel Goleman pada 1995, dan kini diakui sebagai faktor penting dalam kehidupan sosial maupun profesional.
Dalam praktiknya, EQ terlihat dari kemampuan berkomunikasi dengan baik, mudah beradaptasi, mampu bekerja dalam tim, serta punya empati yang tinggi. Bahkan, riset dari TalentSmart menemukan bahwa 90% orang yang punya performa kerja terbaik ternyata memiliki EQ yang tinggi bukan hanya IQ. (TalentSmart, Emotional Intelligence Appraisal Research, 2017)
Di sisi lain, tak sedikit orang yang sangat cerdas secara akademis, tapi justru kesulitan saat harus bekerja dalam tim atau menyelesaikan konflik di lingkungan kerja. Mereka bisa memecahkan soal matematika tingkat tinggi, tapi belum tentu bisa mendamaikan dua rekan kerja yang berselisih.
Studi gabungan antara Harvard University, Stanford Research Institute (bukan universitas Stanford), dan Carnegie Foundation yang berasal dari penelitian klasik pada tahun 1918 oleh Charles Riborg Mann, menyimpulkan bahwa: 85% dari kesuksesan seseorang dalam pekerjaan ditentukan oleh keterampilan interpersonal (soft skills), sementara hanya 15% berasal dari keterampilan teknis (hard skills).
Karena itu, tak cukup hanya mengasah IQ. Kita juga perlu membangun EQ, bahkan juga SQ spiritual intelligence atau kecerdasan spiritual. Kalau IQ membantu kita berpikir logis dan cepat, EQ membantu kita membangun hubungan yang sehat, dan SQ memberi kita kompas nilai dan makna dalam hidup. Ketiganya saling melengkapi. Tanpa EQ dan SQ, orang dengan IQ tinggi bisa saja jadi egois, sulit diajak kerja sama, atau bahkan tidak punya arah hidup yang jelas.
Menurut studi Korn Ferry (2019), pemimpin dengan EQ tinggi mampu mendorong kinerja tim hingga 20% lebih baik dibanding yang hanya mengandalkan kecerdasan intelektual.
Dengan kata lain, bila merujuk pada teori, kalau ingin sukses dan seimbang dalam hidup, jangan cuma pintar secara akademik, jadilah juga pintar secara emosional dan spiritual.
Memaknai Candaan Prabowo
Merujuk pada penjelasan di atas, ucapan Presiden Prabowo “banyak orang pintar justru tidak menjadi apa-apa” meskipun dilontarkan dalam konteks santai, sebetulnya menyimpan kritik sosial yang cukup tajam dan tidak bisa dianggap remeh.
Candaan itu menyentil realitas bahwa kecerdasan intelektual (IQ) yang tinggi saja tidak cukup untuk menjamin kesuksesan seseorang, terutama dalam dunia kerja dan kepemimpinan.
Jika dikaitkan dengan teori Daniel Goleman tentang emotional intelligence, pernyataan ini menjadi refleksi dari kenyataan struktural-bahwa kita masih terlalu mengagungkan "kepintaran akademik". Sementara aspek-aspek penting lain seperti kemampuan beradaptasi, empati, dan etika kerja sering kali diabaikan dalam proses pendidikan maupun rekrutmen kerja.
Fakta di dunia kerja Indonesia menunjukkan bahwa ketimpangan antara penguasaan hard skills dan soft skills semakin nyata dan mengkhawatirkan. Laporan Bank Dunia tahun 2020 mengungkap bahwa lebih dari 50 persen lulusan perguruan tinggi di Indonesia dianggap belum siap terjun ke dunia kerja, terutama karena minimnya keterampilan non-teknis seperti kemampuan komunikasi, manajemen konflik, dan kerja sama tim.
Hal ini sejalan dengan temuan Survei LinkedIn Indonesia tahun 2021 yang mencatat bahwa keterampilan yang paling dicari oleh perusahaan saat ini bukan lagi sekadar kemampuan teknis, melainkan justru adaptability, emotional intelligence, dan kolaborasi.
Bahkan, Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam Rencana Strategis SDM 2023 menyoroti bahwa salah satu tantangan utama dunia kerja kita adalah adanya mismatch antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha di mana ketimpangan ini sebagian besar disebabkan oleh lemahnya penguasaan soft skills.
Dengan latar belakang inilah, pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa “banyak orang pintar justru tidak menjadi apa-apa” meskipun disampaikan dalam nada candaan nyatanya bersandar pada realitas yang serius: banyak lulusan yang ‘cerdas’ secara akademik, namun gagal beraktualisasi karena rendahnya kecerdasan emosional mereka.
Bila ditelaah lebih jauh, ketimpangan antara IQ dan EQ ini sebenarnya berakar pada sistem pendidikan kita yang masih terlalu menekankan aspek kognitif seperti nilai ujian, hafalan, dan kemampuan menjawab soal. Sementara itu, ruang untuk membentuk karakter, menumbuhkan empati, dan mengasah keterampilan sosial masih sangat terbatas.
Dengan kata lain, kita menghadapi ketimpangan struktural dalam pembangunan manusia, di mana sistem pendidikan lebih sibuk mencetak individu ‘pintar’ ketimbang membentuk manusia yang utuh, adaptif, dan berdaya guna sosial. Oleh karena itu, candaan Presiden perlu ditanggapi bukan dengan tawa semata, melainkan sebagai ajakan untuk melakukan refleksi nasional.
IQ di Tengah Era Artificial Intelligence
Di tambah lagi, dewasa ini kita dihadapkan dengan sebuah fenomena baru, yakni perkembangan kecerdasan buatan Artificial Intelligence (AI) yang tengah menciptakan lanskap baru dalam kehidupan sosial dan dunia kerja.
Berbagai pekerjaan yang dulu membutuhkan kemampuan intelektual manusia seperti menulis laporan, menganalisis data, bahkan membuat konten kreatif kini bisa dikerjakan dengan bantuan AI dalam hitungan detik.
Dengan kata lain, kita sekarang hidup di era di mana kecerdasan logis, teknis, dan komputasional tidak lagi menjadi keunggulan eksklusif manusia. IQ hanya sebuah kosmetika intektual yang tan makna. Menjadi remah dalam distrupsi sejarah yang tak terbendung ini. Namun, di tengah disrupsi ini, justru muncul satu dimensi yang tetap tidak tergantikan: kecerdasan emosional.
Kecerdasan emosional adalah buah dari proses panjang yang terbentuk sejak masa kanak-kanak, dibentuk oleh lingkungan keluarga, pendidikan, dan interaksi sosial yang kompleks. Nilai-nilai seperti empati, kasih sayang, kepekaan sosial, serta kemampuan membaca suasana batin orang lain, tidak bisa dilatih lewat algoritma.
Penelitian Daniel Goleman, menegaskan bahwa EQ adalah faktor penentu utama dalam kepemimpinan, kerja tim, dan hubungan sosial yang sehat hal-hal yang sampai hari ini belum bisa direplikasi oleh mesin.
AI, secerdas apa pun, tidak memiliki pengalaman hidup. Ia tidak mengenal kehilangan, tidak merasakan cinta, tidak mengalami konflik batin, dan tidak bisa menangis karena empati. Di sinilah letak perbedaan mendasar antara manusia dan teknologi.
Dalam dunia yang semakin terotomatisasi, justru kecerdasan emosional menjadi “mata uang baru” yang menentukan siapa yang mampu bertahan, beradaptasi, dan memimpin. Mereka yang bisa memahami perasaan, menjaga hubungan, dan menyelesaikan konflik antar-individu, akan menjadi aktor penting di masa depan sebagai penyeimbang dari logika dingin mesin.
Maka, ketika banyak yang khawatir akan kehilangan pekerjaan karena AI, candaan Presiden mestinya bisa diambil sebagai renungan kebangsaan. Dimana kita justru perlu menggali keunggulan khas manusia: menjadi makhluk yang bisa merasa dan peduli.
Indonesia Emas 2045
Dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045, kurikulum pendidikan kita jangan hanya berfokus kepada peningkatan kecerdasan intelektual semata, tetapi juga harus memberi ruang yang besar bagi pengembangan kecerdasan emosional melalui pendidikan karakter.
Sebab tak ada satupun IQ manusia yang bisa melawan AI dengan gudang Big Data nya. Individu atau bangsa yang tak memiliki kecerdasan emosional atau karakter, hanya bisa menjadi subsistem dalam mega sistem Artificial Intelligence. Hanya individu dan bangsa yang berkarakter yang mampu men-challenge dan men-absorb kedigjayaan era digital ini.
Indonesia, dengan kekayaan budaya dan nilai-nilai ketimuran yang menjunjung tinggi tata krama dan sopan santun, sesungguhnya memiliki modal sosial yang sangat kuat untuk membentuk pribadi-pribadi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga matang secara emosional dan spiritual.
Nilai-nilai luhur bangsa seperti persatuan, toleransi, gotong royong, dan tenggang rasa penting ditanamkan sejak dini kepada generasi muda. Inilah generasi yang diharapkan mampu memimpin masa depan dengan hati, akal, dan nurani. Mungkin inilah trajectory dari candaan Presiden.
***
*) Oleh : Dr. Rudi Pradisetia Sudirdja, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa, Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (ASPERHUPIKI).
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
______
*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |