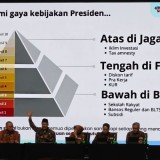TIMES MALANG, MALANG – Setiap pergantian kepemimpinan nasional selalu membawa dua wajah: harapan dan keraguan. Harapan akan munculnya energi baru untuk membenahi bangsa, dan keraguan bahwa perubahan hanya akan berganti kulit tanpa mengubah isi. Inilah paradoks abadi dalam politik Indonesia bahwa reformasi sering kali berhenti di slogan, bukan pada substansi.
Kini, di tengah peralihan kekuasaan menuju pemerintahan baru, publik kembali dihadapkan pada pertanyaan mendasar: apa yang sesungguhnya berubah dari kepemimpinan negara kita?
Kepemimpinan negara bukan sekadar urusan siapa yang memegang tampuk kekuasaan, melainkan tentang bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Sejarah politik Indonesia memperlihatkan, setiap transisi kekuasaan selalu diikuti oleh harapan besar akan arah baru bangsa.
Namun sering kali, struktur birokrasi, watak politik, dan pola komunikasi kekuasaan justru tetap berputar dalam orbit lama: sentralistik, elitis, dan kurang sensitif terhadap suara publik. Maka, perubahan kepemimpinan sejatinya bukan diukur dari figur baru yang naik, melainkan dari cara baru negara hadir dalam kehidupan rakyatnya.
Perubahan sejati menuntut transformasi kepemimpinan, bukan sekadar regenerasi politik. Kita membutuhkan pemimpin yang bukan hanya pandai mengelola kekuasaan, tapi juga sanggup menata peradaban.
Dalam bahasa Max Weber, kepemimpinan karismatik yang berorientasi pada visi moral harus menggeser kepemimpinan rasional-instrumental yang berorientasi pada kekuasaan administratif. Pemimpin bukan hanya manajer negara, tapi juga guru bangsa yang mampu menumbuhkan kesadaran kolektif, bukan sekadar mengatur kebijakan.
Namun sayangnya, politik modern kita masih terlalu sibuk dengan kalkulasi elektoral. Demokrasi berubah menjadi ritual lima tahunan, di mana kepemimpinan diukur dari elektabilitas, bukan dari integritas.
Dalam konteks itu, perubahan kepemimpinan kerap kehilangan makna ideologis. Pergantian presiden bisa saja membawa narasi pembangunan baru, tetapi apakah narasi itu menumbuhkan martabat kemanusiaan dan menegakkan keadilan sosial?
Di sinilah publik perlu kembali kritis karena keberhasilan pemerintahan bukan hanya soal pembangunan infrastruktur, tetapi juga pembangunan karakter bangsa.
Kepemimpinan negara di era globalisasi dan kecerdasan buatan seperti sekarang juga menghadapi tantangan baru: krisis kepercayaan dan erosi moral publik. Dunia digital mengubah cara rakyat menilai pemimpin bukan lagi melalui pidato, tetapi melalui tindakan nyata yang terekam dalam ingatan publik digital.
Pemimpin yang gagal membaca perubahan zaman akan kehilangan legitimasi moral di hadapan generasi yang lebih kritis. Di tengah derasnya arus informasi dan percepatan teknologi, pemimpin yang dibutuhkan bukan yang paling kuat, tetapi yang paling adaptif, transparan, dan empatik.
Kita memerlukan kepemimpinan yang sanggup mengelola perbedaan tanpa menindas, yang mampu memimpin dialog di tengah polarisasi politik yang kian mengeras. Indonesia hari ini bukan lagi negara yang kekurangan sumber daya, melainkan negara yang sering kehilangan arah karena lemahnya visi kepemimpinan yang berkeadaban.
Kepemimpinan nasional harus kembali berpijak pada nilai dasar konstitusional: kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Sebab sejatinya, kekuasaan tanpa arah nilai hanya akan menghasilkan kebijakan tanpa jiwa.
Dalam setiap perubahan pemerintahan, kita selalu mendengar jargon “melanjutkan yang baik, memperbaiki yang kurang.” Tetapi kalimat itu hanya akan berarti jika dibarengi dengan keberanian moral untuk mengoreksi diri.
Negara tidak cukup hanya dipimpin oleh ahli strategi; ia harus juga dituntun oleh orang bijak yang sanggup berkata “cukup” di tengah godaan kekuasaan yang tak terbatas. Seorang pemimpin sejati bukan hanya membangun jalan raya, tetapi juga menyiapkan jalan bagi generasi masa depan yang berpikir bebas dan berakhlak mulia.
Kepemimpinan bangsa ke depan perlu bergeser dari pola command and control menuju collaborate and empower. Rakyat bukan lagi objek yang diatur, melainkan subjek yang dilibatkan. Demokrasi sejati bukan tentang siapa yang berkuasa, tetapi sejauh mana kekuasaan itu memanusiakan.
Dalam konteks itu, pergantian presiden seharusnya menjadi momentum untuk mereformulasi hubungan antara negara dan rakyat dari relasi kuasa menjadi relasi kepercayaan.
Pada akhirnya, perubahan kepemimpinan negara tidak akan bermakna apa pun tanpa reformasi mental di tubuh penyelenggara negara dan kesadaran kritis di kalangan rakyat. Rakyat yang diam adalah pintu masuk bagi kekuasaan yang sewenang-wenang. Karena itu, kontrol sosial dan keberanian bersuara harus menjadi bagian dari budaya demokrasi, bukan sekadar reaksi politik.
Kita boleh berganti pemimpin, tapi jangan sampai kehilangan arah. Kita boleh berpindah rezim, tapi jangan sampai kehilangan cita-cita. Bangsa ini tidak sedang kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang mau jujur memimpin. Dan pada titik itu, perubahan kepemimpinan bukan tentang siapa yang naik ke puncak, melainkan siapa yang berani menundukkan diri pada suara nurani rakyat.
***
*) Oleh : Iswan Tunggal Nogroho, Praktisi Pendidikan.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |