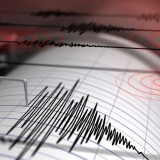TIMES MALANG, MALANG – Unggahan Presiden Prabowo Subianto di media sosial muncul dengan pola yang mudah dikenali. Dalam satu pekan, publik bisa melihatnya berada di tengah prajurit, lalu di hari berikutnya duduk bersama warga, kemudian berpindah menghadiri acara resmi di istana.
Setiap visual berdiri sendiri sebagai potret kegiatan harian, tetapi ritmenya yang konsisten membuatnya tampil sebagai rangkaian yang membentuk kesan utuh tentang sosok yang sedang memimpin negara. Foto-foto itu tidak selalu disertai pernyataan panjang. Namun dalam ruang digital, absennya kalimat tidak mengurangi kekuatan pesan yang dapat ditangkap publik.
Media sosial membuat visual bekerja lebih cepat dibandingkan kata-kata. Pengguna sering melihat gambar terlebih dahulu sebelum membaca konteksnya. Pola konsumsi informasi semacam ini memungkinkan teori framing yang diperkenalkan Erving Goffman bekerja sangat kuat di ruang digital.
Goffman menjelaskan bahwa manusia menafsirkan realitas menggunakan bingkai tertentu, semacam lensa yang membuat bagian tertentu dari peristiwa tampak lebih penting daripada yang lain. Di media sosial, bingkai tercipta melalui sudut kamera, pencahayaan, komposisi, pilihan momen, serta cara gambar itu dibagikan. Setiap elemen memberi warna pada cara publik memahami foto seorang presiden.
Robert Entman memperjelas konsep framing dengan menyebut dua proses utama: seleksi dan penonjolan. Ketika suatu aspek dipilih untuk ditampilkan, aspek lain otomatis mundur ke latar. Ketika aspek yang sama diulang dalam banyak unggahan, publik akan menganggapnya sebagai hal yang penting.
Prinsip ini terlihat jelas dalam unggahan Prabowo. Foto dirinya berdiri tegap bersama prajurit memperkuat kesan kedisiplinan dan kewibawaan. Foto saat ia berbincang dengan petani atau warga kecil mempertegas citra kedekatan dan kepedulian. Tidak ada pernyataan eksplisit yang menjelaskan maksud gambar itu, tetapi publik dapat membaca pesan yang muncul dari pola pengulangan.
Gestur kecil dalam politik digital bisa menjadi pesan besar. Publik memperhatikan detail cara presiden mencondongkan tubuh saat mendengar seseorang berbicara, posisi tangan ketika menyapa, atau ekspresi wajah saat berdiri di tengah kerumunan.
Detail-detail ini, yang dulu mungkin hanya sekilas tertangkap kamera televisi, kini beredar luas dalam bentuk foto yang dapat diulang dilihat kapan saja. Orang tidak menunggu penjelasan panjang. Visual langsung bekerja membentuk kesan emosional yang mudah mengendap dan sulit dilawan oleh argumen yang datang belakangan.
Ruang digital memperluas panggung front stage sebagaimana dijelaskan Goffman. Jika sebelumnya front stage muncul dalam forum resmi seperti pidato kenegaraan, wawancara televisi, atau rapat terbuka, kini panggung itu hadir di layar ponsel.
Presiden tampil dalam berbagai suasana, formal maupun informal, dan publik menyaksikannya dari jarak yang tampak sangat dekat. Yang terlihat sebenarnya hanya bagian tertentu dari keseluruhan peristiwa. Ada proses panjang, diskusi internal, dan dinamika birokrasi yang tidak pernah masuk dalam frame. Visual selalu menyisakan ruang kosong, dan ruang kosong itu diisi publik dengan tafsir mereka sendiri.
Proses seleksi semakin terlihat dalam kegiatan resmi. Banyak foto biasanya diambil oleh tim dokumentasi dari berbagai sudut. Hanya satu atau dua yang akhirnya dipublikasikan. Foto yang dipilih bukan sekadar dokumentasi, tetapi juga keputusan editorial. Ketika foto yang dipilih menampilkan presiden sedang mendengarkan dengan wajah serius, kesan kepemimpinan yang fokus dan tegas muncul di benak publik.
Jika yang dipilih foto presiden tersenyum lebar bersama warga, kesan hangat dan merakyat menjadi lebih menonjol. Pilihan-pilihan seperti ini menunjukkan bagaimana framing bekerja dalam praktik sehari-hari, meski tidak selalu dirumuskan secara formal sebagai strategi kampanye.
Media sosial juga membawa jenis kedekatan baru. Publik merasa mengikuti presiden dari hari ke hari. Mereka tahu ia sedang berada di mana, sedang bertemu siapa, dan terlibat dalam kegiatan apa saja, meskipun semua itu hanya hadir lewat layar.
Kedekatan semu ini menciptakan hubungan yang terasa personal, walaupun sebenarnya tetap dibatasi oleh jarak dan filter kurasi. Foto hanya menunjukkan apa yang ada di depan lensa. Ruang di luar frame, baik secara fisik maupun politis, tetap tidak tersentuh.
Keterbatasan visual tetap perlu diperhitungkan. Foto tidak dapat menjelaskan konteks kebijakan, dinamika perencanaan, maupun perdebatan yang terjadi sebelum sebuah keputusan diambil.
Visual hanya menangkap permukaan peristiwa. Publik sering menafsirkan permukaan itu sebagai representasi kenyataan, padahal kenyataan pemerintahan jauh lebih kompleks dan berlapis. Kekuatan visual terletak pada kecepatannya menyentuh emosi, bukan pada kelengkapannya menggambarkan situasi.
Pergeseran cara publik menerima informasi membuat visual memegang peran yang dahulu banyak dipegang pidato, tajuk rencana, atau laporan panjang media. Kini sebuah foto bisa menjangkau jutaan orang dalam hitungan menit tanpa perlu perantara redaksi.
Unggahan Prabowo memperlihatkan bagaimana pola ini bekerja dalam praktik politik Indonesia. Ia hadir dalam berbagai peristiwa, dan kehadiran itu direkam dalam bentuk gambar yang segera menyebar. Untuk sebagian orang, ini dianggap sebagai bukti kerja dan komitmen. Untuk sebagian lain, ini dipandang sebagai bagian dari upaya pembingkaian citra.
Di luar itu, masih ada peran media dan masyarakat sipil yang ikut menguji dan menafsirkan ulang visual tersebut. Liputan mendalam, laporan investigatif, dan diskusi publik dapat memperluas atau justru mengoreksi makna awal yang dilekatkan pada sebuah gambar.
Relasi antara foto resmi, pemberitaan media, dan percakapan warganet membentuk ekosistem makna yang bergerak. Dalam ekosistem inilah citra kepemimpinan dinegosiasikan dari hari ke hari.
Cara publik menafsirkan visual tidak hanya bergantung pada gambar itu sendiri, tetapi juga pada bingkai pemikiran yang sudah lebih dulu mereka miliki. Goffman menyebut pertemuan antara bingkai pesan dan bingkai audiens ini sebagai penyelarasan frame.
Ketika keduanya selaras, pesan visual diterima tanpa banyak resistensi. Ketika keduanya bertentangan, gambar yang sama bisa dibaca dengan kecurigaan atau kritik. Ruang digital memungkinkan semua pembacaan itu hidup berdampingan, saling bersilang di kolom komentar, tanpa harus mencari satu makna tunggal.
Teori framing membantu menjelaskan bahwa visual politik bukan sekadar soal estetika, tetapi juga soal kekuasaan mendefinisikan realitas. Siapa yang memegang kendali atas pemilihan gambar, sudut pandang, dan waktu unggah, memiliki kesempatan lebih besar memengaruhi cara publik memahami peristiwa.
Unggahan Prabowo menjadi salah satu contoh konkret bagaimana proses itu bekerja di Indonesia hari ini. Citra yang muncul di layar bukan sepenuhnya fiktif, tetapi juga bukan cermin utuh dari keseluruhan realitas.
Foto-foto di media sosial memperlihatkan bagian cerita yang ingin dibagikan. Bagian lain tetap berada di luar frame, berlangsung tanpa sorotan kamera, dan jarang masuk ke ruang perbincangan sehari-hari.
Publik berhadapan dengan potongan-potongan ini setiap hari, lalu menyusunnya menjadi gambaran sendiri tentang kepemimpinan. Di titik itu, politik visual menemukan kekuatannya. Bukan hanya pada apa yang ditampilkan, tetapi juga pada apa yang dibiarkan tak terlihat dan diisi oleh imajinasi masing-masing orang.
***
*) Oleh: Tiara Delia Natasha.
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |