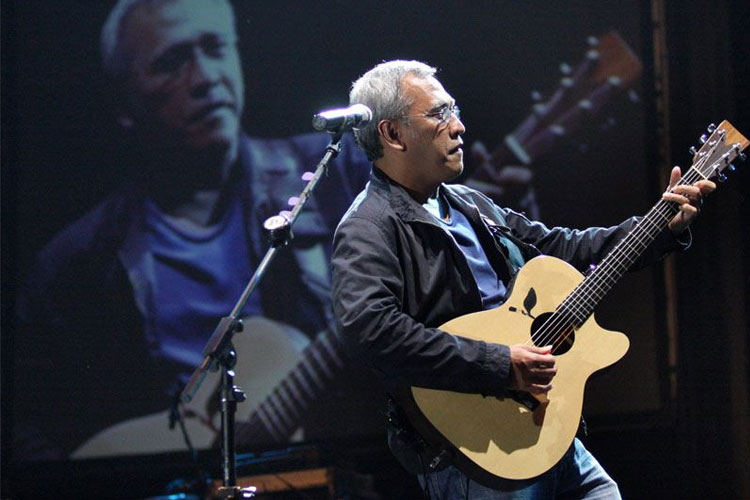TIMES MALANG, MALANG – Sejak Senin, 25 Agustus 2025, gelombang unjuk rasa membesar di berbagai penjuru negeri. Pemicunya adalah isu yang sangat dekat dengan rasa keadilan publik, rencana kenaikan tunjangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Di tengah kesulitan ekonomi yang masih terasa, kabar ini menyulut kemarahan. Rakyat merasa aspirasinya sekali lagi diabaikan oleh para wakil yang seharusnya mereka layani. Turun ke jalan menjadi pilihan paling sahih untuk menyuarakan kegusaran.
Awalnya, energi kolektif itu begitu murni. Mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil bersatu padu dalam satu tuntutan yang jelas. Namun, takdir berkata lain. Sebuah insiden tragis mengubah arah angin secara drastis. Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online berusia 21 tahun, tewas mengenaskan, terlindas kendaraan taktis Brigade Mobil (Brimob).
Kematian Affan adalah bensin yang disiramkan ke bara api. Duka seketika berubah menjadi amarah yang meluap-luap. Demonstrasi yang semula berpusat pada kritik kebijakan, kini membawa dendam atas nyawa yang hilang.
Simpati publik terhadap perjuangan para demonstran mencapai puncaknya. Namun, di titik inilah, di tengah emosi yang membuncah, kewaspadaan kita mulai mengendur.
Dalam hitungan hari, wajah demonstrasi berubah menjadi kian beringas. Asap hitam mengepul dari fasilitas umum yang terbakar. Etalase toko-toko pecah, isinya dijarah. Kota-kota yang semula menjadi panggung aspirasi demokrasi kini terasa seperti medan perang kecil.
Di tengah kekacauan ini, suara-suara sumbang mulai terdengar, berbisik di linimasa media sosial. “Sudah cukup,” kata mereka. “Demonstrasi ini sudah ditunggangi. Ini bukan lagi perjuangan murni.”
Seruan agar warga tidak lagi turun ke jalan menyebar cepat, didasari argumen yang masuk akal; keselamatan. Lebih jauh, banyak yang mulai menuding adanya operasi ‘false flag’, sebuah taktik licik di mana sebuah pihak melakukan kekerasan untuk kemudian menimpakan kesalahan pada lawan politiknya.
Tujuannya jelas: mendelegitimasi gerakan, menciptakan citra anarkis, dan memberi pembenaran bagi aparat untuk melakukan tindakan represif yang lebih keras.
Apa yang kita saksikan selama sepekan terakhir ini adalah contoh bagaimana bagaimana sebuah gerakan sosial yang tulus dapat dibajak. Wasisto Raharjo Jati, seorang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menyebutnya sebagai fenomena “penumpang gelap”.
Mereka adalah aktor-aktor baik individu maupun kelompok yang menyusup ke dalam kerumunan dengan membawa agenda tersembunyi. Kepentingan mereka bukan pada tuntutan awal, melainkan pada pemanfaatan momentum untuk tujuan politik atau bahkan ekonomi pribadi.
Kita bisa melihat dengan jelas bagaimana para penumpang gelap ini bekerja. Pertama, terjadi pergeseran musuh. Fokus yang tadinya tajam mengarah pada kebijakan DPR, kini dibelokkan menjadi konfrontasi fisik melawan aparat keamanan di lapangan.
Kemarahan atas meninggalnya Affan dieksploitasi habis-habisan untuk melanggengkan siklus kekerasan. Akibatnya, narasi publik bergeser dari “rakyat melawan kebijakan wakilnya” menjadi “rakyat melawan polisi”. Siapa yang diuntungkan dari pergeseran ini? Tentu saja para anggota dewan yang kebijakannya kini luput dari sorotan.
Kedua, munculnya kekerasan dan penjarahan yang sistematis. Sulit untuk percaya bahwa para mahasiswa atau buruh yang dengan sadar memperjuangkan keadilan, tiba-tiba berubah menjadi perusak dan penjarah.
Aksi perusakan fasilitas publik dan penjarahan oleh kelompok-kelompok terorganisir adalah distraksi paling brutal. Mereka adalah provokator bayaran yang sengaja menciptakan kekacauan untuk menodai citra perjuangan. Mereka memberi amunisi bagi narasi bahwa para demonstran adalah gerombolan anarkis yang harus ditertibkan dengan kekerasan.
Ketiga, penyebaran isu sektarian. Di tengah kerumunan dan di media sosial, mulai muncul ajakan untuk menyerang kelompok minoritas tertentu, menuduh mereka sebagai dalang kerusuhan.
Ini adalah taktik pecah belah paling purba dan paling berbahaya. Solidaritas rakyat yang telah terbangun lintas suku, agama, dan ras, coba dirobek-robek dengan sentimen kebencian. Tujuannya adalah memecah kekuatan massa menjadi faksi-faksi kecil yang saling curiga.
Bahkan, aksi simpatik seperti “silaturahmi ke rumah keluarga Affan” pun bisa menjadi distraksi yang subtil. Meski tampak mulia, pengorganisasiannya secara masif dapat mengalihkan energi dari tuntutan perubahan sistemik menjadi sekadar tindakan karitatif.
Tragedi Affan seharusnya menjadi simbol kegagalan negara dalam melindungi warganya dan momentum untuk menuntut akuntabilitas, bukan hanya menjadi kisah pilu yang selesai dengan sumbangan dan doa bersama.
Lalu, haruskah kita menyerah dan pulang? Haruskah kita membiarkan para penumpang gelap ini memenangkan pertarungan narasi? Tentu tidak. Mundur berarti membiarkan suara kita dibungkam dan demokrasi kita dimanipulasi. Tantangan kita saat ini bukanlah untuk berhenti berjuang, melainkan untuk berjuang dengan lebih cerdas.
Kini, setiap individu yang peduli pada nasib bangsa ini memiliki tugas baru, yaitu menjadi filter informasi dan penjaga nalar. Kita perlu lebih mahir dalam mengidentifikasi siapa kawan sejati dalam perjuangan dan siapa benalu yang hanya ingin merusak.
Ketika melihat sebuah aksi di jalan atau unggahan di media sosial, tanyakan pada diri sendiri: Apakah ini akan mendekatkan kita pada tuntutan awal? Ataukah ini justru menjauhkan kita, memecah belah, dan mengundang represi yang lebih besar?
Melawan narasi palsu dan para freerider ini menuntut kita untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam atas isu yang diusung. Kita tidak bisa lagi hanya bermodal semangat.
Kita perlu membekali diri dengan pengetahuan, data, dan argumen yang kuat. Energi kolektif yang luar biasa ini harus diarahkan kembali pada target yang sesungguhnya: menuntut akuntabilitas dan kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Kematian Affan Kurniawan adalah luka yang mendalam bagi demokrasi kita. Jangan biarkan pengorbanannya sia-sia karena perjuangan ini dibajak oleh mereka yang tak bertanggung jawab.
Saatnya kita merapatkan barisan, bukan untuk saling menyerang, melainkan untuk saling melindungi. melindungi dari provokasi, melindungi dari hoaks, dan melindungi api reformasi agar tidak padam ditiup angin kekacauan.
Mari saling menjaga, demi panjangnya umur demokrasi kita. Perjuangan ini masih panjang, dan satu-satunya senjata yang paling kita butuhkan saat ini adalah “kewarasan”.
***
*) Oleh : Ahmad Ulul Albab, M.Pd., Kepala Sekolah SDN 5 Ampelgading.
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |