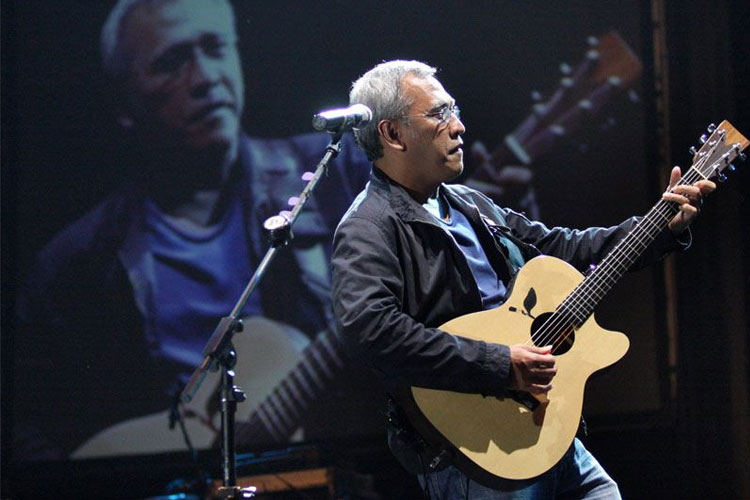TIMES MALANG, MALANG – Politik, kata orang bijak, adalah seni mengelola kemungkinan. Tetapi di negeri ini, politik lebih sering menjelma jadi panggung sandiwara, di mana para aktornya sibuk memainkan peran untuk mempertahankan kekuasaan ketimbang melayani rakyat.
Sementara rakyat sendiri, yang semestinya jadi penonton sekaligus pemilik panggung, dipaksa puas hanya dengan menelan janji manis yang retak di bibir.
Kita baru saja menyaksikan bagaimana arus demonstrasi merebak di berbagai kota. Suara massa di jalanan kembali menjadi alarm keras bagi pemerintahan. Apa yang mereka teriakkan sesungguhnya bukan sekadar tuntutan teknis, melainkan jeritan panjang dari rasa muak pada praktik politik yang kian jauh dari nurani publik.
Pertanyaannya, mengapa protes jalanan terus berulang? Jawabannya sederhana: karena kekuasaan politik di negeri ini lebih sibuk menjaga singgasana daripada menjawab keresahan rakyat.
Sejatinya, politik itu adalah kompas arah bangsa. Tapi di tangan elit, kompas itu kerap diputar sesuai kepentingan kelompok.
Keputusan penting negara mulai dari soal sumber daya, kebijakan ekonomi, hingga hukum lebih banyak ditentukan lewat lobi di ruang-ruang gelap daripada musyawarah di ruang terang.
Ketika kekuasaan hanya dipandang sebagai “alat transaksi”, maka rakyat hanyalah mata uang yang bisa ditukar kapan saja.
Tak heran jika demonstrasi muncul sebagai bentuk koreksi. Jalanan menjadi “parlemen alternatif” ketika parlemen resmi dianggap lumpuh oleh kepentingan politik.
Kita bisa melihat, demo terbaru bukan hanya luapan emosi, tetapi simbol bahwa legitimasi kekuasaan perlahan tergerus. Sebab rakyat sudah paham, janji-janji reformasi yang dulu diagungkan kini hanya jadi fosil yang dipajang di rak sejarah.
Namun, kekuasaan punya wajah yang licin. Alih-alih menjawab tuntutan, kekuasaan sering menebalkan tameng: memperbanyak aparat, memperkeras regulasi, bahkan tak jarang menstigma gerakan rakyat sebagai ancaman.
Inilah wajah paradoks demokrasi kita. Negara yang katanya berdiri di atas kedaulatan rakyat, justru gagap ketika rakyat berteriak.
Kalau kita telisik lebih jauh, problem utama ada pada arsitektur politik itu sendiri. Partai politik yang semestinya menjadi jembatan aspirasi, kini berubah jadi pabrik tiket kekuasaan.
Lalu ketika sudah duduk di kursi empuk, sebagian besar elit lebih memilih melayani kepentingan oligarki ketimbang suara pemilihnya. Maka tak heran jika pemerintah terlihat “takluk” pada tekanan segelintir kelompok, sementara jutaan suara di jalanan hanya dianggap riuh sesaat.
Analogi sederhana: negara ini ibarat kapal besar yang sedang terombang-ambing di tengah badai. Nahkoda dan awak kapal mestinya kompak menjaga arah. Tapi apa yang terjadi?
Mereka sibuk berebut kemudi, sibuk menawar arah angin, bahkan ada yang tega membocorkan lambung kapal demi keuntungan pribadi. Maka, tak heran jika para penumpang rakyat mulai berteriak histeris, bahkan sebagian memilih melompat ke laut sebagai bentuk perlawanan.
Kita tidak bisa menutup mata bahwa demo terbaru hanyalah satu bab dari novel panjang perjalanan demokrasi kita. Gelombang protes itu adalah refleksi ketidakpuasan yang terus menumpuk: dari korupsi yang tak kunjung reda, mafia-mafia yang bercokol di setiap sektor, hingga ketimpangan sosial yang kian menganga. Jika kekuasaan tidak segera berbenah, jangan salahkan rakyat bila jalanan menjadi ruang belajar politik paling efektif bagi generasi muda.
Argumentasi bahwa kekuasaan politik mempengaruhi situasi pemerintahan bukan sekadar teori. Lihatlah, setiap tarik-ulur di tingkat elit selalu berimbas langsung pada stabilitas negara.
Ketika elit berseteru, harga kebutuhan melonjak. Ketika elit berkompromi, kebijakan publik bisa berubah arah hanya dalam semalam. Singkatnya, nasib jutaan rakyat sering ditentukan oleh secuil kesepakatan yang terjadi di ruang rapat tertutup.
Inilah yang harus kita kritisi bersama: demokrasi yang dikebiri, politik yang dikuasai oligarki, dan kekuasaan yang kerap lupa diri. Jika kondisi ini dibiarkan, maka demo demi demo hanya akan menjadi gema tanpa jawaban. Padahal suara rakyat di jalanan adalah cermin yang seharusnya membuat penguasa bercermin, bukan malah memecahkan kaca.
Kini, bola ada di tangan mereka yang berkuasa. Apakah mereka mau membuka telinga dan hati, atau justru menutup rapat kedua-duanya? Sejarah telah membuktikan, kekuasaan yang tuli pada jeritan rakyat hanya akan berakhir dengan kejatuhan yang tragis.
Dan kepada kita semua, rakyat biasa, demo bukan sekadar turun ke jalan. Ia adalah simbol bahwa suara kita masih ada, bahwa demokrasi belum mati sepenuhnya. Sebab ketika suara rakyat benar-benar padam, saat itulah demokrasi berubah jadi makam.
***
*) Oleh : Hainor Rahman, Kader PMII Cabang Kota Malang.
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |