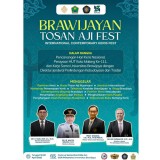TIMES MALANG, MALANG – Di era media sosial yang serba instan, kemunculan fenomena flexing atau pamer kekayaan menjadi tren yang kian mencemaskan. Terutama di kalangan generasi Z yang lahir dan tumbuh bersama internet, gawai, dan algoritma flexing telah menjelma menjadi gaya hidup sekaligus standar pencapaian yang baru.
Di balik kilauan barang mewah, liburan glamor, dan pencitraan semu itu, tersembunyi racun yang perlahan menggerogoti kesehatan mental, nilai-nilai sosial, dan integritas generasi muda kita.
Berbagai studi psikologis menunjukkan bahwa terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain di media sosial dapat memicu kecemasan, depresi, dan krisis identitas. Ketika standar kebahagiaan digeser menjadi standar visual yang palsu dan penuh pencitraan, banyak dari mereka yang merasa tertinggal, gagal, atau tidak berharga.
Selain aspek psikologis, flexing juga mendorong perilaku konsumtif yang berlebihan. Generasi Z yang seharusnya menabung untuk masa depan atau mengembangkan kapasitas diri justru terjerumus pada pola hidup “gaji habis demi konten”. Tidak sedikit yang membeli barang-barang bermerek dengan sistem cicilan atau bahkan utang hanya demi eksistensi digital.
Lebih parahnya lagi, flexing telah menggeser nilai-nilai sosial. Dulu, seseorang dihargai karena kontribusi, etika kerja, dan pencapaian nyata. Kini, tak jarang yang dihargai hanya karena tampilan dan "gaya hidup".
Fenomena flexing telah menciptakan norma sosial baru yang semu tentang menilai sebuah keberhasilan yaitu bahwa keberhasilan adalah tentang apa yang tampak, bukan apa yang sesungguhnya diraih.
Yang lebih mengkhawatirkan, budaya ini bisa menjadi pintu masuk bagi perilaku tidak etis. Munculnya kasus-kasus penipuan, pencucian uang, dan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan demi gaya hidup mewah bukanlah isapan jempol. Dalam banyak kasus, flexing bukan hanya mencerminkan konsumerisme, tetapi juga menutupi realitas dan menjustifikasi ketidakjujuran.
Kita tidak bisa membicarakan flexing tanpa menyentuh soal media sosial dan algoritmanya. Platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube memiliki sistem yang mendorong konten visual yang mencolok dan memicu emosi.
Konten flexing mudah viral karena memadukan daya tarik visual dengan unsur aspiratif yang membuat penonton ingin memiliki gaya hidup serupa.
Dengan algoritma yang mengutamakan interaksi dan sensasi, pengguna pun cenderung mengulang pola yang sama demi keterkenalan. Dalam ekosistem seperti ini, konten edukatif, reflektif, dan membumi menjadi kalah saing.
Akibatnya, flexing terus beranak-pinak dan membentuk kultur digital yang toksik. Meskipun fenomena flexing tampak menjamur, bukan berarti tidak ada jalan keluar.
Berikut beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan untuk meredam dampak buruknya:
Pertama, Pendidikan literasi digital sejak dini. Sekolah, keluarga, dan pemerintah harus bekerja sama untuk membekali generasi Z dengan kemampuan literasi digital, khususnya dalam mengenali konten palsu, manipulatif, dan merugikan secara psikologis. Literasi digital juga mencakup pemahaman bahwa tidak semua yang tampak di media sosial adalah kenyataan.
Kedua, Mendorong konten positif dan otentik. Kreator konten dan influencer perlu didorong, bahkan diberi insentif untuk membuat konten yang edukatif, inspiratif, dan jujur. Platform digital juga perlu lebih aktif mempromosikan nilai-nilai positif, bukan hanya mengejar klik dan engagement.
Ketiga, Membangun budaya produktif, bukan konsumtif. Generasi Z perlu diarahkan untuk fokus pada pengembangan diri dan produktivitas. Pelatihan keterampilan, kewirausahaan, serta proyek-proyek sosial harus diperbanyak agar mereka melihat bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh merek barang yang dipakai atau jumlah followers di media sosialnya, melainkan oleh kontribusi dan karya nyata dalam kehidupan.
Keempat, Regulasi iklan dan endorsement. Banyak konten flexing yang sebenarnya merupakan bagian dari iklan terselubung. Pemerintah melalui otoritas terkait seperti Komdigi dan KPI dapat mengatur lebih ketat soal transparansi iklan, endorsement, dan konten digital agar publik tidak terus-menerus terjebak ilusi.
Kelima, Menumbuhkan kesadaran diri dan komunitas. Akhirnya, perubahan harus dimulai dari dalam. Generasi Z perlu diajak merenung: apakah kebahagiaan sejati datang dari pengakuan orang lain, atau dari penerimaan terhadap diri sendiri? Komunitas, baik di sekolah, kampus, maupun media sosial, bisa menjadi ruang yang sehat untuk saling mendukung tanpa tekanan pamer.
Di tengah derasnya arus digital, kita perlu kembali menata ulang paradigma keberhasilan dan kebahagiaan. Bahwa yang sejati bukanlah yang dipamerkan, tetapi yang berdampak. Bahwa menjadi berharga tidak harus ditunjukkan dengan barang mahal, tetapi dengan integritas dan kebermanfaatan.
Flexing adalah racun yang menyusup secara halus melalui layar gawai kita, mengubah cara pandang, rasa syukur, hingga arah hidup generasi muda. Tetapi dengan kesadaran kolektif, regulasi yang tepat, dan pendidikan yang membumi, racun ini bisa dinetralisir. Generasi Z layak mendapatkan masa depan yang lebih sehat dari segi mental, sosial, dan spiritual.
***
*) Oleh : Dony Purnomo, Guru Geografi SMAN 1 Purwantoro.
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |