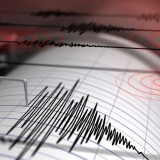TIMES MALANG, MALANG – Indonesia sering membranding diri sebagai negara tangguh bencana. Setiap tahun, instansi pemerintah memamerkan simulasi evakuasi, pelatihan relawan, dan dokumentasi heroik aparat di lokasi bencana. Tetapi, di balik itu semua, ada ironi yang tak bisa ditutup-tutupi: negara kita terlalu sibuk menjadi pemadam kebakaran, namun minim visi menjadi penjaga rumah dari bara api.
Pada titik inilah persoalan tata kelola bencana perlu dikupas lebih dalam bukan soal seberapa cepat respon datang saat tragedi terjadi, tetapi seberapa kuat negara mencegah tragedi itu lahir dari kelalaian sistemik.
Indonesia bukan sekadar “rawan bencana,” tetapi berada tepat di episentrum risiko global. Statistik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari tiga ribu kejadian per tahun, mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi, likuefaksi, angin puting beliung, hingga kekeringan ekstrem.
Dengan posisi geografis dan geologis seperti ini, kesiapsiagaan nasional seharusnya menjadi prioritas kebijakan, bukan hanya proyek yang muncul musiman ketika bencana besar trending di media sosial.
Persoalan utama kita bukan ketidaktahuan akan risiko, tetapi kegagalan mengelola pengetahuan menjadi kebijakan konkret. Hampir setiap laporan investigasi pascabencana menunjukkan pola berulang: kerusakan lebih besar disebabkan oleh kelalaian tata ruang, pembiaran eksploitasi wilayah, lemahnya regulasi lingkungan, alih fungsi lahan tanpa kendali, serta minimnya edukasi mitigasi di tingkat masyarakat. Bencana alam pada akhirnya berubah menjadi bencana sosial akibat kesalahan manusia yang sebetulnya dapat dicegah.
Contoh konkret paling nyata terlihat dalam berbagai banjir besar di sejumlah kota besar dan wilayah pesisir. Tahun demi tahun pemerintah menyalahkan curah hujan ekstrem, tetapi mengabaikan fakta bahwa garis sempadan sungai diokupasi bangunan permanen, hutan lindung diganti perumahan, dan izin pertambangan diberikan tanpa pengawasan.
Negara hadir saat banjir datang dengan karung beras, tenda darurat, dan konferensi pers. Tetapi negara tidak hadir saat pengembang memodifikasi lahan sembarangan atau ketika keputusan politik merestui operasi tambang di kawasan penyangga air. Tatkala itu, negara seolah tuli, buta, dan lumpuh.
Kita juga perlu mengkritisi romantisasi relawan dan aparat penolong sebagai wajah utama mitigasi bencana. Masyarakat memang mengapresiasi pengorbanan mereka. Namun patut diakui, keberanian dan profesionalitas mereka sering menjadi tameng yang menutupi kesalahan aktor kebijakan yang gagal membangun sistem pencegahan. Semakin heroik narasi penyelamatan di lokasi bencana, semakin kabur pertanyaan mendasar: mengapa bencana sebesar itu bisa terjadi lagi dan lagi di tempat yang sama?
Di negara-negara maju yang memiliki sistem tata kelola risiko matang, mitigasi dilakukan jauh sebelum bencana datang, bukan sambil berduka. Jepang, misalnya, tidak menunggu gempa menghancurkan kota untuk mengenalkan kurikulum mitigasi bencana di sekolah.
Selandia Baru tidak menunggu tsunami menghantam barulah mengatur tata ruang wilayah pesisir. Tetapi di Indonesia, kurikulum literasi kebencanaan masih sebatas formalitas, ditinjau hanya setelah bencana besar menjadi headline nasional.
Sayangnya, sistem birokrasi kita masih menganggap kebencanaan sebagai urusan teknis BNPB dan BPBD, bukan sebagai arsitektur kebijakan nasional lintas sektor. Padahal, mitigasi harus terhubung dengan Kementerian PUPR (tata ruang), KLHK (hutan dan lingkungan), Kementerian Pendidikan (edukasi dan kurikulum), Kementerian Keuangan (prioritas anggaran), hingga aparat penegakan hukum untuk mengawasi pelanggaran pemanfaatan ruang. Selama kebencanaan hanya dipandang sebagai urusan operasional penyelamatan, Indonesia akan terus membayar mahal akibat politik pembiaran terhadap risiko.
Selain itu, anggaran penanggulangan bencana masih sangat reaktif. Dana siap pakai untuk penanganan darurat disediakan besar, tetapi anggaran untuk mitigasi jangka panjang jauh lebih kecil. Ini menimbulkan pertanyaan: apakah mitigasi memang tidak diprioritaskan, atau karena mitigasi tidak menawarkan profit politik sebesar penanganan darurat?
Tidak bisa dipungkiri, pencitraan pejabat di tengah banjir atau di lokasi evakuasi sering kali lebih populer daripada kerja sunyi membuat standar bangunan tahan gempa atau merevisi tata ruang wilayah.
Tata kelola bencana bukan hanya tentang kesiapsiagaan aparat, bukan tentang infrastruktur evakuasi, bukan tentang berapa banyak tenda BNPB mampu didirikan dalam sehari. Tata kelola yang baik berarti negara hadir sebelum bencana, bukan hanya saat bencana menghantam.
Negara harus berani menjalankan kebijakan yang tidak populis: menutup tambang ilegal, mencabut izin pengembang yang melanggar jalur sempadan sungai, menindak kepala daerah yang mengabaikan analisis dampak lingkungan, memindahkan permukiman dari zona merah, dan memastikan kurikulum mitigasi masuk sekolah sejak dini.
Bencana adalah bagian dari hidup di Nusantara. Tetapi derita berkepanjangan akibat bencana berulang tidak boleh menjadi takdir. Indonesia membutuhkan paradigma baru: dari “respons bencana” menuju “manajemen risiko dan pencegahan.”
Negara harus berhenti merayakan heroisme di tengah puing-puing, dan mulai membangun sistem yang mencegah puing-puing itu lahir. Inilah revolusi kebijakan yang paling mendesak dan kalau gagal diwujudkan, kita akan terus menjadi bangsa yang lebih gaduh di saat bencana, tetapi hening ketika penyebab bencana sedang dipelihara.
***
*) Oleh : Abdul Aziz, S.Pd., Praktisi Pendidikan.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |