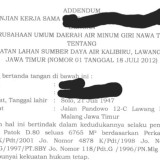TIMES MALANG, JAKARTA – Korupsi di ranah hukum lebih dari sekadar pelanggaran etik; ia menghambat arus investasi, memicu krisis kepercayaan pelaku usaha, dan menyusutkan daya fiskal negara untuk mendorong pertumbuhan.
Dampaknya menjalar ke luar dinding peradilan, menyelimuti sektor ekonomi dengan ketidakpastian, menahan laju pembangunan, dan memperlemah sendi makroekonomi seperti partikel halus yang tak kasat mata namun terus menggerogoti fondasi pembangunan secara perlahan.
Sepanjang 2011–2024, sebanyak 29 hakim terbukti menerima suap dengan akumulasi hingga Rp109 miliar lebih (ICW, 2025). Teranyar, 7 hakim terjerat suap dengan total 60 miliar (Tempo, 2025). Angkanya—meski tampak “kecil” dibanding PDB—justru telah menandakan terciptanya ekosistem jualbeli putusan yang sistemik.
Praktik ini menambah biaya transaksi tersembunyi bagi pelaku usaha, mereduksi kepastian hukum, dan menaikkan countryrisk premium. Satu vonis dapat mengubah peta investasi: proyek tertunda, modal asing berbelok, dan industri dalam negeri kehilangan daya saing.
Artinya, ketika proses peradilan ternoda, efek rambatnya menyentuh banyak simpul ekonomi sekaligus. Lonjakan premi risiko membuat investor menuntut imbal hasil lebih tinggi, bank menaikkan suku bunga kredit, dan UMKM kehabisan likuiditas. Di sisi fiskal, penerimaan negara tergerus karena denda dinegosiasikan, aset sitaan tak optimal, dan potensi pajak hilang akibat inefisiensi korporasi.
Kompetisi pasar pun terseret dalam penyimpangan; pelaku usaha yang mengikuti aturan justru sering kalah bersaing dengan pihak yang menempuh jalur curang, menciptakan distorsi persaingan yang menggerus daya saing nasional. Pada saat yang sama, defisit kepercayaan publik merebak, merusak sentimen konsumen dan memicu capital outflow menyempurnakan lingkaran tekanan terhadap perekonomian.
Riset lintas negara berkembang, seperti yang dilakukan Edgardo Buscaglia (1999), pernah menunjukkan setiap kenaikan satu poin indeks korupsi yudisial memangkas investasi hingga 0,5 % PDB. Di Indonesia, korelasi serupa tampak saat skandal pengadilan merebak: IHSG tergelincir, sovereign bond yield melebar, dan belanja pembangunan terpaksa dipangkas demi membayar bunga utang tambahan.
Belajar dari Mahkamah Agung Amerika, Sidney A. Shapiro dan Joseph P. Tomain, dalam How Government Built America (2024), mencatat bahwa di era Franklin D. Roosevelt pengadilan tinggi AS awalnya “propasar”, kerap melindungi bisnis dari regulasi.
Namun ketika kebebasan pasar berbenturan dengan kepentingan rakyat, Mahkamah Agung berani bergeser: mendukung dan memperkuat perlindungan sosial, dan menegaskan nilai kesetaraan serta keadilan ekonomi.
Pesan dari dua pakar hukum ini jelas: lembaga peradilan bukan sekadar wasit yang meniup peluit panjang dalam perkara yang sangat runyam sekalipun, melainkan penjaga nilai fundamental negara siap menepis korupsi atau monopoli bila merugikan kesejahteraan bersama.
Pertanyaannya kemudian, mengapa problem ini persisten di Indonesia? Karena reformasi struktural sering mentok dengan kultur patronase. Proses rekrutmen hakim masih rawan titipan, penegakan etik baru bergulir setelah skandal terkuak, sementara upaya meninjau ulang vonis ringan sering tersendat di level administrasi.
Tanpa insentif positif remunerasi kompetitif serta sanksi finansial progresif (penyitaan aset keluarga), korupsi dalam proses hukum menjadi beban diam-diam yang pada akhirnya dibayar masyarakat dalam bentuk mahalnya hidup dan hilangnya layanan publik.
Pradeep S. Mehta (2022), Sekretaris Jenderal Consumer Unity & Trust Society International, menekankan konsep inclusive adjudication: Hakim seharusnya menakar eksternalitas ekonomi dan pihak tak terwakili. Sementara praktiknya masih positivistik; pemulihan kerugian negara sebatas angka formal, mengabaikan opportunity loss semisal hilangnya lapangan kerja atau transfer teknologi.
Jalan keluarnya menuntut pendekatan berlapis. Pertama-tama, setiap perkara tipikor perlu disertai audit forensik ekonomi sehingga hakim melihat kerugian bukan semata angka formal, melainkan rangkaian efek dari jam kerja yang hilang hingga tekanan fiskal sebelum mengetuk hukuman denda.
Transparansi juga krusial: informasi aset hasil penyitaan semestinya dipublikasikan secara terbuka dan waktu nyata melalui sistem daring agar proses akuntabilitas berjalan dan celah korupsi tertutup.
Pada saat yang sama, Indonesia membutuhkan pengadilan komersial terpadu yang mempertemukan hakim karier dengan ekonom dan analis risiko; komposisi ini membuat putusan tidak lepas dari sasaran pembangunan jangka panjang. Upaya tersebut harus dibarengi skema remunerasi berbasis kinerja: tunjangan atau bonus baru boleh cair jika target pemulihan aset tercapai dan rekam jejak etik bersih.
Terakhir, ekosistem pelapor mesti disuburkan lewat imbalan yang diambil langsung dari dana sitaan—whistleblower reward progresif—sehingga biaya fiskal pengawasan berkurang, sementara keberanian masyarakat meningkat.
Sebetulnya, fondasi teknis sudah mulai terbentuk. KPK dan BPKP sesekali melampirkan hitungan kerugian makro dalam berkas perkara, meski belum wajib. Sementara Kejaksaan Agung telah memiliki aplikasi inventarisasi barang rampasan, tetapi data itu belum tersambung otomatis dengan portal aset rampasan KPK maupun dashboard Pengadilan Tipikor. Demikian gagasan pengadilan komersial multidisiplin pun tidak jelas; tunjangan hakim memang naik, tetapi belum diikat pada keberhasilan memulihkan aset.
Dengan kata lain, Indonesia memiliki serpihan solusi audit ekonomi, dasbor aset lintaslembaga, panel ahli, insentif kinerja, hingga whistleblower reward, namun serpihan itu belum disatukan ke dalam sistem terpadu, sehingga dampaknya masih terasa setengah hati.
Pada sisi lain, konsekuensinya memang sangat nyata, yakni putusan mudah diatur/dibeli dan kontraktor atau pengusaha yang korup pun lolos hukuman, proyek-proyek vital seperti jalan tol dan bendungan kerap dibangun tidak sesuai spesifikasi, menyisakan risiko kegagalan struktural dan pemborosan anggaran.
Ketika terjadi kerusakan, biaya perbaikan berulang dialihkan ke APBN, menekan anggaran kesehatan dan pendidikan. Bank Dunia (2024) mengestimasi inefisiensi proyek akibat korupsi yudisial menelan 0,3 % PDB per tahun cukup membangun 3000 puskesmas atau 20.000 beasiswa doktoral.
Distorsi itu menambah biaya logistik 1,2 % PDB, mengerek harga bahan pokok 0,8 % di kawasan timur, dan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia 0,4 poin dalam satu dekade. Dari kenyataan itu dapat kita simpulkan bahwa setiap rupiah yang hilang di pengadilan bukan sekadar angka audit, melainkan detak jantung layanan publik yang tertunda. Pertanggungjawaban hukum oleh para hakim tidak menunjukkan kepastian dan menjamin keadilan bagi negara.
Terakhir, saya mau katakan bahwa ketidakberesan hukum memberi dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat: harga barang meningkat, dan biaya distribusi pun ikut melonjak. Selama palu keadilan ternoda, suap rupiah berlipat ganda menjadi bunga utang, proyek tambalsulam, serta kesempatan kerja yang semakin sempit.
Membersihkan meja hijau bukan sekadar agenda etika. Lebih dari itu, tanpa operasi besar-besaran memperbaiki lembaga yudisial, korupsi akan terus menggerogoti semua sumber daya, memupuk kemakmuran semu, dan memicu krisis kepercayaan publik.
***
*) Oleh : Igrissa Majid, Alumni STHI Jentera.
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |