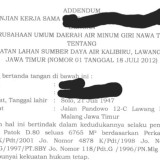TIMES MALANG, MALANG – Sound horeg, alias sound system berdaya tinggi yang menyebabkan kebisingan ekstrem kini resmi masuk daftar ‘terlarang’ oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur.
Lewat Fatwa Nomor 1 Tahun 2025, MUI menyatakan bahwa penggunaan sound horeg hukumnya haram jika menimbulkan mudarat, seperti mengganggu orang lain, gangguan pendengaran, kecemasan, gangguan aktivitas belajar, gangguan kesehatan, dan kerusakan bangunan akibat getaran.
Sejak diumumkan, fatwa ini langsung bikin gaduh media sosial. Ada yang mengacungkan jempol, ada yang pasang mode debat.
Dukungan terhadap fatwa ini datang dari kalangan yang selama ini merasa ‘tersakiti’ oleh dentuman bass berjam-jam tanpa ampun. Warga di desa-desa, apalagi lansia, orang sakit, dan anak-anak kecil, merasa sound horeg seringkali mengacaukan ritme hidup mereka. Bukan hanya soal kerasnya suara, tapi juga soal waktu dan durasinya yang sering tak kenal kompromi.
Di banyak kasus, bahkan pesta kecil bisa mendadak jadi panggung konser mini yang bikin lingkungan tak bisa tidur sampai lewat tengah malam.
Tapi tentu, tidak semua orang ikut mendukung fatwa itu. Sejumlah seniman, pemilik jasa sewa sound system, hingga para panitia hajatan tradisional justru merasa ‘disunat’ ruang kreativitas dan mata pencaharian mereka. Misalnya ada yang menyuarakan bahwa kalau ekonomi rakyat tumbuh lewat kegiatan tersebut, kenapa justru dibatasi?
Baginya, selama volume bisa dikontrol dan waktu pelaksanaan tidak mengganggu, sound horeg bukan kriminal. Lagi pula, dalam banyak komunitas pedesaan, penggunaan sound horeg bukan sekadar alat tapi simbol ekspresi.
Di sinilah benturan antara dua poros kepentingan muncul: kemaslahatan publik vs kebebasan individu dan ekonomi kreatif rakyat. Apakah segala bentuk gangguan berarti harus diharamkan? Bagaimana dengan konteks budaya lokal yang menjadikan suara keras sebagai bagian dari ritual sosial dan simbol kebahagiaan?
Seperti biasa, jawabannya tidak sesederhana mengatur volume speaker. Kita perlu menyelami niat, konteks, dan dampaknya, bukan hanya menuding ‘salah’ atau ‘benar’ secara hitam-putih.
Maka, daripada menjadikan fatwa sebagai ujung tombak larangan semata, mengapa tidak kita jadikan sebagai trigger lahirnya kesadaran baru dalam berkegiatan di ruang publik? Bahwa merayakan kebahagiaan itu hak, tapi menjaga kenyamanan dan hak orang lain itu juga wajib.
Kita perlu mencari titik temu: regulasi volume, jam tayang, edukasi akustik, hingga inovasi teknologi soundproofing. Fatwa bukan akhir, tapi bisa menjadi awal dialog yang sehat antara agama, budaya, dan nalar publik yang saling menghormati.
Fatwa dalam Gelombang Dentuman
Ketika suara dentuman sound system lebih keras daripada suara azan, barangkali sudah saatnya kita bertanya: apa sebenarnya yang sedang kita rayakan? Kebisingan? Atau pergeseran nilai-nilai sosial? Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang keharaman penggunaan sound horeg lahir dari kegelisahan atas fenomena yang kian meluas ini.
Fatwa ini bukan semata reaksi emosional, melainkan hasil ijtihad kolektif yang mempertimbangkan aspek syariat, sosial, kesehatan, dan psikologis masyarakat.
Dalam dokumennya, MUI Jatim menyebutkan bahwa sound horeg dapat merusak fasilitas umum atau barang milik orang lain, membahayakan dan mengganggu kesehatan, dan juga terjadi percampuran dimana laki-laki dan wanita saling berjoget dan membuka aurat serta kemungkaran lain dan karenanya, jika membawa lebih banyak mudarat, penggunaannya haram secara syariat.
Secara argumentatif, fatwa ini berpijak pada prinsip la dharar wa la dhirar tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dalam maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam), menjaga jiwa (hifdz an-nafs), menjaga akal (hifdz al-aql), dan menjaga harta (hifdz al-mal) menjadi pilar utama.
Dentuman berlebihan yang membangunkan anak kecil, mengusik istirahat orang sakit, mengganggu lansia, atau merusak fasilitas umum jelas bertentangan dengan semangat Islam yang menjunjung rahmah dan keseimbangan.
Tak hanya itu, fatwa ini juga memperhatikan dampak lingkungan, seperti polusi suara yang oleh WHO telah dikategorikan sebagai ancaman kesehatan masyarakat modern.
Namun, fatwa ini tidak muncul tanpa tantangan. Penolakan datang dari sebagian pelaku usaha event organizer, pemilik persewaan sound system, bahkan sebagian masyarakat yang menilai bahwa fatwa tersebut terlalu judgemental dan tidak akomodatif terhadap budaya lokal.
Di beberapa wilayah, sound horeg dianggap sebagai bagian dari tradisi: simbol kebahagiaan, status sosial, hingga solidaritas komunitas. Mereka yang menolak fatwa ini khawatir, jangan-jangan yang dibungkam bukan sekadar speaker, tapi juga ekspresi budaya rakyat kecil.
Di titik ini, publik justru dihadapkan pada pertanyaan penting: apakah setiap budaya layak dipertahankan meski mengganggu kemaslahatan umum? Sebaliknya, apakah fatwa keagamaan bisa diberlakukan tanpa mendialogkan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat?
Solusinya barangkali bukan pada pelarangan total atau pembiaran total, tapi pada pembentukan standar etis bersama. MUI Jatim sendiri menyertakan catatan penting: bahwa penggunaan sound system diperbolehkan selama tidak menimbulkan mudarat dan sesuai kebutuhan yang wajar.
Celah ini bisa menjadi ruang kolaboratif antara ulama, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menyusun regulasi teknis. Baik dari sisi jam operasional, batas decibel maksimal, hingga zona-zona bebas suara keras.
Fatwa ini, kalau dimaknai dengan bijak, bukanlah bentuk pelarangan semata, melainkan panggilan moral agar masyarakat belajar membedakan antara meriah dan merusak, antara rayakanlah dan hargailah.
Jika suara kita menjadi sebab telinga orang lain menderita, mungkin saatnya volume diturunkan dan empati dinaikkan. Dalam dunia yang makin bising, siapa tahu suara yang paling beradab adalah yang tahu kapan harus diam.
Bersuara dengan Nurani, Berpesta dengan Empati
Akhirnya, persoalan sound horeg bukan sekadar perkara kerasnya volume, tapi juga tentang seberapa dalam kita mendengar suara sesama-suara kegembiraan, suara kelelahan, suara tradisi, juga suara permohonan agar bisa tidur dengan tenang.
Fatwa memang bisa membimbing, tapi harmoni hanya lahir ketika semua pihak bersedia saling mendekat, bukan saling mendebat. Karena itu, mari bersuara dengan nurani, dan bersenang-senang dengan empati.
Solusinya bisa dimulai dari hal sederhana tapi berdampak besar: edukasi publik tentang etika suara, penjadwalan jam karnaval, festival, atau sejenisnya yang manusiawi, hingga kerja sama antara pemilik sound system dan tokoh masyarakat untuk membuat pedoman volume yang sehat.
Pemerintah daerah bisa menyediakan “zona ekspresi budaya” dengan standar akustik ramah lingkungan. Bahkan, teknologi bisa diajak ikut berfatwa menggunakan limiter suara, pengukur decibel real-time, atau penyekat suara portabel di tempat terbuka.
Dalam perspektif kesehatan, ini bukan sekadar soal telinga berdenging, tapi juga soal gangguan tidur, stres anak-anak, dan iritasi emosional lansia. Dalam ranah sosial, ini menyangkut kepekaan akan ruang bersama yang perlu dijaga, bukan dikuasai. Secara psikologis, pesta tak perlu membebani orang lain.
Secara ekonomi, penyedia jasa bisa tetap hidup asal mampu beradaptasi menawarkan paket "sound friendly" sebagai bentuk inovasi. Dan secara keagamaan, bukankah syukur yang paling indah adalah yang membuat orang lain ikut tenang dan nyaman?
Bayangkan jika di setiap pesta, tuan rumah tidak hanya berkata “silakan makan,” tapi juga berkata, “kami sudah mengatur agar suara tidak mengganggu.” Itu bukan sekadar keramahan, tapi bentuk iman sosial yang nyata. Di situlah letak peradaban kita diuji, bukan hanya pada seberapa tinggi kita bersuara, tapi seberapa halus kita mendengarkan.
Maka, mari kita rayakan kehidupan dengan cara yang lebih bijak. Agar desa tak kehilangan budayanya, kota tak kehilangan kedamaiannya, dan masyarakat tak kehilangan rasa saling menghargainya.
Karena sejatinya, dalam simfoni hidup bersama, nada paling indah adalah ketika semua bisa terdengar tanpa saling menenggelamkan.
***
*) Oleh : Achmad Diny Hidayatullah, ASN UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Khodim Madrasah Diniyah Shirotul Huda, Tlogomas Malang.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |