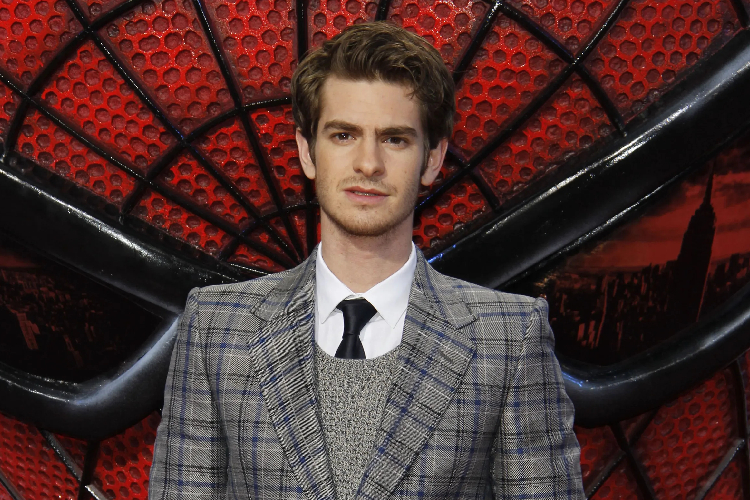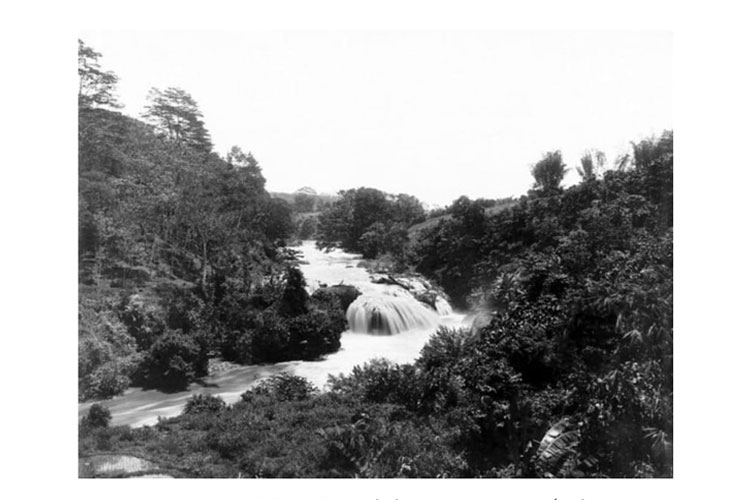TIMES MALANG, JAKARTA – Tak dapat dibayangkan apabila ada institusi negara yang bisa menyadap, mengawasi ruang digital, merekrut penyidik lembaga lain, mengintervensi proses penyidikan, dan memiliki unit intelijen yang bisa menggalang informasi, dan menindak atas nama “kepentingan nasional” semua itu tanpa pengawasan yang memadai dan tanpa transparansi kepada public memiliki power full bercokokolan di Negara ini.
Begitulah kira-kira gambaran dari “momok” dimasa depan yang berkamuflase dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia jika Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri disahkan. RUU ini bukan revisi menuju reformasi, tapi revisi menuju konsentrasi kekuasaan. Polri akan secara eksplisit sedang diarahkan menjadi lembaga superpower: kuat, luas, dan leluasa, namun nyaris tanpa control.
Jika benar disahkan, dan prosesnya tak jauh berbeda dengan UU TNI, maka kita benar-benar sedang berada di jalan menuju negara “pentungan” atau "tuan senjata” seperti halnya era Orde Baru. Bukan karena semua Polisi dan TNI jahat, tapi sistem yang dibangun membuka ruang terlalu besar untuk penyalahgunaan kekuasaan. Negara hukum yang sehat tidak membiarkan satu lembaga memiliki terlalu banyak kekuasaan tanpa akuntabilitas. Karena kekuasaan yang besar, tanpa kontrol, bukan hanya menggoda, tapi juga merusak.
Dengan itu semua mari kita sejenak merubah highlight kita dari UU TNI kepada RUU Polri yang menurut kabar dan gelagatnya akan segara dibahas oleh DPR, pasca atau secara simultan dibahas dengan RUU KUHAP.
Demokrasi dalam Bahaya, Kekuasaan Tanpa Batas di Depan Mata
RUU ini tidak menjawab masalah-masalah mendasar dalam tubuh Polri, seperti tingginya angka kekerasan, lemahnya keterbukaan, hingga buruknya pelayanan publik. Alih-alih diperbaiki malah justru sebaliknya, ia malah diperluas kewenangannya ke ranah-ranah yang seharusnya tidak dikendalikan oleh satu lembaga saja. Ini sama sekali bukan untuk pembenahan kelembagaan, melainkan pergeseran kekuasaan yang sangat mengkhawatirkan.
Dalam draft yang tersebar, kita dapat menyaksikan upaya sistematis pemberian kewenangan super pada Polri. Ini bukan lagi polisi sipil, tapi polisi yang menjelma dalam suatu system yang absolut. Ketika ada lembaga penegak hukum yang diberi kewenangan menggunakan senjata memiliki kekuatan dan kewenangan yang mendekati keabsolutan
Maka kita sebenarnya tengah melangkah mundur, kembali ke era otoritarianisme terselubung. Demokrasi membutuhkan batasan-batasan kekuasaan, bukan justru sebaliknya, karna pada akhirnya akan menjadikan suatu lembaga atau institusi seperti “peluru tak terkendali”.
Karna lewat RUU itu ia leluasa menyadap, memantau ruang siber, mengelola intelijen, dan bahkan mengintervensi kerja lembaga penegak hukum lain seperti KPK dan PPNS. Mereka bisa memblokir informasi digital, mengawasi aktivitas warga di dunia maya, dan mengendalikan penyidikan dari hulu ke hilir. Ini jelas berpotensi membungkam kebebasan sipil dan menggerus prinsip-prinsip demokrasi.
Siber dan Intelijen: Celah Represif yang Dilegalkan, Siapa bisa Melawannya?
RUU ini juga membuka jalan bagi Polri untuk masuk terlalu jauh ke wilayah lembaga penegakan hukum lain. Mulai dari menentukan siapa yang boleh menjadi penyidik, memberikan supervisi, bahkan “memeriksa hasil penyidikan” lembaga lain sebelum diserahkan ke kejaksaan. Ini bukan sekadar pengawasan, tapi control yang cukup ketat dan lagi-lagi nyaris absolut.
Maka tak dapat dielakkan apabila lembaga se-independent KPK bisa dengan mudahnya dikooptasi. PPNS yang seharusnya bekerja atas nama kementerian teknis akan kehilangan independensinya juga. Semua alur hukum yang semula terdistribusi akan terpusat di bawah satu komando: Polri.
Dengan usulan perubahan pada Pasal 14 ayat 1 huruf G menyatakan bahwa Polri diberikan wewenang untuk mengoordinasikan, mengawasi, dan membina secara teknis kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), penyidik lain yang diatur oleh undang-undang, serta satuan pengamanan swakarsa. Koalisi Masyarakat Sipil memandang ketentuan ini berpotensi menjadikan Polri sebagai lembaga 'super investigator' dengan kekuasaan yang terlalu besar.
Kemudian Pasal 16 ayat 1 huruf Q memberi Polri wewenang untuk memantau hingga memblokir ruang siber. Dengan dalih “keamanan dan ketertiban”, semua bentuk ekspresi digital bisa dipelintir menjadi ancaman.
Kita sudah pernah lihat ini saat internet di Papua dipadamkan tahun 2019 dan sekarang, pemadaman seperti itu akan dilegalkan dan dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan kementrerian Komunikasi dan Digital serta Badan Siber dan Sendi Negara (BSSN).
Lalu Pasal 16 A dan 16 B memperluas peran Direktorat Intelkam, yang bisa menyelidiki, menggalang, bahkan menindak sesuatu yang dianggap mengganggu “kepentingan nasional”. Tapi siapa yang mendefinisikan kepentingan itu? Jika tidak jelas, ini bisa menjadi tiket bebas untuk menekan kebebasan sipil atas nama keamanan.
Trakhir Pasal 30 ayat 2 dalam draf RUU Polri yang mengusulkan perpanjangan usia pensiun bagi anggota kepolisian. Jika ketentuan ini diberlakukan, maka usia pensiun akan diperpanjang menjadi 60 tahun, dengan ketentuan khusus bagi anggota yang memiliki keahlian tertentu hingga 62 tahun, dan bagi pejabat fungsional hingga 65 tahun. Usulan ini mendapat penolakan dari masyarakat sipil karena dinilai dapat menghambat proses regenerasi dalam institusi Polri serta memperburuk persoalan menumpuknya perwira tinggi.
Tanpa penjelasan hukum yang eksplisit, RUU ini banyak melegitimasi praktik penyadapan yang bisa dilakukan Polri. Di KPK, penyadapan butuh izin Dewan Pengawas. Di Polri? Tak ada yang mengatur secara ketat. Ini menciptakan ruang gelap dalam praktik pengawasan dan pengumpulan informasi dari semua kalangan masyarakat, maka bisa saja target utama ialah mereka yang selalu melontarkan teriakan kritis terhadap pemerintah.
Lebih gila lagi, usia pensiun anggota Polri diperpanjang, bahkan bisa diperpanjang kembali atas putusan presiden. Ini membuat rantai komando bisa berlangsung sangat lama dan menutup regenerasi. Bila digunakan untuk mempertahankan kekuasaan orang-orang tertentu, ini bisa menjadi alat politik, dan bukan alat negara.
Catatan Kelam, Bukan Asumsi Kosong
Ini semua bukan asumsi kosong. Data dan laporan dari Komnas HAM, KontraS, YLBHI, LBH Masyarakat, ICW, AJI, dan lembaga-lembaga sipil lainnya sudah menunjukkan bahwa Polri adalah lembaga negara paling banyak dilaporkan dalam kasus pelanggaran HAM, kekerasan, penyiksaan, hingga praktik koruptif. Alih-alih diperbaiki, malah ingin diberi kuasa lebih besar.
Publik selama ini menuntut agar Polri dibenahi: dibuat lebih transparan, diawasi secara efektif, dan dijauhkan dari politik praktis. Tapi gelagat RUU ini justru mengukuhkan Polri sebagai kekuatan tunggal yang bisa memenetrasi batas-batas demokrasi yang selama ini dijaga ketat oleh masyarakat Indonesia.
Semua kekhawatiran terhadap perluasan kewenangan Polri melalui RUU ini bukan sekadar teori atau prasangka buruk. Ini adalah alarm yang dibunyikan berdasarkan data nyata—rekam jejak panjang yang menunjukkan bagaimana institusi ini belum mampu menjalankan kekuasaan yang ada secara profesional, apalagi ketika kekuasaannya akan diperluas.
KontraS, dalam pemantauan selama 2020 hingga awal 2024, mencatat ribuan peristiwa kekerasan yang melibatkan aparat kepolisian. Ratusan kasus tiap tahunnya, termasuk penembakan, penganiayaan, penyiksaan, hingga pembunuhan di luar proses hukum (extrajudicial killing).
Hanya dalam 4 bulan pertama 2024, sudah tercatat 198 kasus. Ini bukan lembaga yang butuh lebih banyak kuasa—ini lembaga yang butuh pembenahan mendalam. YLBHI pun menegaskan kekhawatiran yang sama. Sepanjang 2019, setidaknya 67 orang meninggal dengan dugaan kuat sebagai korban extrajudicial killing oleh polisi.
Dalam setahun (2022–2023), mereka mencatat 130 kasus pelanggaran oleh kepolisian, termasuk kriminalisasi, penahanan sewenang-wenang, intimidasi, hingga pembunuhan di luar hukum. Semua ini adalah bentuk-bentuk kekuasaan yang sudah disalahgunakan, bahkan tanpa adanya payung legalistik seperti yang disiapkan dalam RUU ini.
Lalu, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) mendokumentasikan bagaimana kekerasan sudah menjadi bagian dari proses hukum itu sendiri. Di tiga rutan di Jakarta, selama Januari–Mei 2024, puluhan tahanan mengaku disiksa, diperas, bahkan mengalami kekerasan seksual. Dan mayoritas mereka tidak mendapat bantuan hukum yang layak. Kalau kekuasaan yang sekarang saja sudah sebegitu brutalnya, lalu bagaimana nanti kalau semua itu dilegalkan oleh revisi undang-undang?
Komnas HAM mencatat kepolisian sebagai lembaga dengan aduan pelanggaran HAM tertinggi selama lima tahun terakhir secara konsisten. Dari 744 aduan tahun 2019 hingga 771 aduan tahun 2023. Angka itu bukan cuma statistik; itu adalah indikator betapa lemahnya akuntabilitas internal institusi ini.
Begitu juga dengan Ombudsman RI yang menyoroti maladministrasi kronis di tubuh Polri. Selama 2020–2023, kepolisian selalu berada di puncak daftar lembaga yang paling banyak diadukan. Laporan-laporan itu meliputi penyalahgunaan wewenang, pelayanan buruk, hingga diskriminasi dan tindakan sewenang-wenang.
Kompolnas, yang notabene adalah lembaga resmi yang mengawasi kinerja Polri, turut mencatat ikhwal 1.150 pengaduan hanya sampai September 2023. Kalau lembaga pengawas internal saja penuh dengan pengaduan, apa kabar ketika lembaga ini diberi hak menyadap dan memblokir informasi tanpa kontrol yang ketat?
Jurnalis pun tak luput dari represivitas ini. AJI menghimpun, 15 serangan terhadap jurnalis oleh polisi di tahun 2022. Saat demo Omnibus Law tahun 2020, ada 28 jurnalis jadi korban kekerasan oleh aparat. Padahal dalam negara demokrasi, jurnalis adalah penjaga gerbang informasi publik. Ketika mereka dihajar, yang dihancurkan bukan hanya fisik mereka—tapi juga hak publik untuk tahu atas suatu situasi dan kondisi.
Dari sisi korupsi, Polri juga bukan lembaga tanpa noda. ICW mengungkap praktik-praktik pengadaan gas air mata dan amunisi yang diduga melibatkan tender fiktif dan mark-up harga. Bisnis ilegal seperti Konsorsium 303 yang diduga melibatkan jenderal aktif hingga kasus narkoba dengan pelaku petinggi polisi seperti Irjen Teddy Minahasa dan AKP Andri Bustami semuanya jadi cermin betapa kacaunya mekanisme pengawasan dan etika di internal Polri.
Maka tak mengherankan apabila hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2023 menempatkan kepercayaan publik terhadap Polri di posisi paling rendah dibanding institusi penegak hukum lainnya: hanya 64%. Bahkan dalam survei khusus lembaga pemberantasan korupsi, Polri hanya dipercaya oleh 61% responden—terendah pula
RUU Polri ini bukan sekadar perlu direvisi, tapi harus ditolak secara total. Kita butuh pembaruan Polri yang berpihak pada profesionalisme dan akuntabilitas, bukan yang memperbesar kuasa dan mempersempit kebebasan rakyat.
Kalau DPR dan Pemerintah terus memaksakan RUU ini, maka jelas mereka sedang membangun fondasi otoritarianisme baru dengan seragam coklat dan pangkat bintang. Dan seperti yang sejarah ajarkan: sekali rakyat kehilangan kontrol atas aparat, maka yang hilang bukan hanya demokrasi tapi juga rasa aman kita semua.
Tolak RUU Polri, Haruskah Kekuasaan Sebesar Itu Diberikan Lagi?
RUU Polri ini bukan sekadar perlu direvisi, tapi harus ditolak secara total. Kita butuh pembaruan Polri yang berpihak pada profesionalisme dan akuntabilitas, bukan yang memperbesar kuasa dan mempersempit kebebasan rakyat.
Kalau DPR dan Pemerintah terus memaksakan RUU ini, maka jelas mereka sedang membangun fondasi otoritarianisme baru dengan seragam coklat dan pangkat bintang. Dan seperti yang sejarah ajarkan: sekali rakyat kehilangan kontrol atas aparat, maka yang hilang bukan hanya demokrasi tapi juga rasa aman kita semua.
Dengan rekam jejak seperti itu, haruskah kita percaya bahwa menambahkan kekuasaan ke tangan Polri akan dapat menyelesaikan masalah? Jawabannya jelas: tidak. Bukan karena kita anti-polisi. Tapi karena demokrasi yang sehat tidak boleh memberikan kekuasaan luar biasa kepada lembaga yang belum bisa mempertanggungjawabkan kekuasaan yang sudah ada.
RUU Polri bukanlah jalan menuju reformasi kepolisian. Ia adalah jalan pintas menuju negara polisi. Sebuah negara di mana hukum ditegakkan untuk membungkam, bukan melindungi. Di mana institusi bersenjata lebih berkuasa dari suara rakyat. Dan sejarah sudah cukup mengajarkan: setiap negara yang berjalan ke arah itu, tak pernah berakhir baik.
Maka, Satu Kata: Tolak! RUU ini bukan revisi, tapi regresi. Kita butuh reformasi kepolisian yang berbasis pada HAM, akuntabilitas, dan profesionalitas. Bukan yang berbasis pada senjata, penyadapan, dan kekuasaan tunggal. Maka dengan itu tolak RUU Polri sekarang, sebelum semuanya terlambat.
***
*) Oleh : Bagaskara Dwy Pamungkas, Tim Kaderisasi Nasional PB PMII 2024-2027.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |