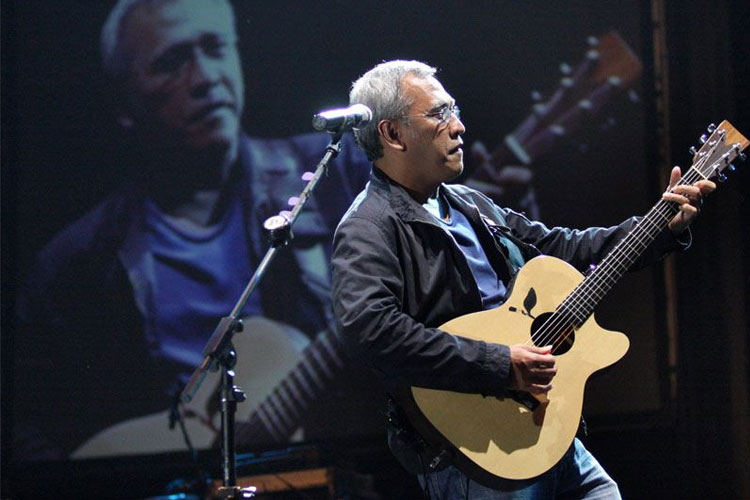TIMES MALANG, MALANG – Peraturan Daerah di Kota Malang baru-baru ini dibuat untuk mengatur pungutan pajak sebesar 10% bagi usaha dengan omzet minimal Rp15 juta per bulan. Kebijakan ini tentunya mengejutkan karena iklim ekonomi Indonesia masih fluktuatif dan belum stabil sepenuhnya. Para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah tentu saja merasa keberatan akan beban tambahan yang harus mereka pikul.
Bagi pemerintah kota Malang kebijakan ini bertujuan untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD), namun pada sisi lainnya kebijakan ini bisa menekan pertumbuhan ekonomi lokal yang selama ini ditopang oleh UMKM.
Sebagai salah satu kota dengan jumlah mahasiswa terbesar di Indonesia, UMKM menjadi tulang punggung ekonomi kota Malang. Seharusnya UMKM dilindungi dan didukung bukan justru dibebani yang membuat mereka terseok-seok.
Apalagi ekonomi Indonesia belum sepenuhnya baik akibat pemulihan pasca pandemi. Pelaku usaha kecil masih harus terus berjuang dan bertahan di tengah lesunya daya beli masyarakat dan juga naiknya harga bahan baku.
Mayoritas pelaku UMKM di Indonesia memiliki omzet bulanan antara Rp5 juta hingga Rp30 juta. Sehingga dengan ambang batas omzet Rp15 juta per bulan, peraturan ini akan menyasar mayoritas UMKM di kota Malang.
Kebijakan ini akan mempengaruhi usaha-usaha seperti kedai makanan lokal, toko kelontong, usaha laundry, kedai kopi hingga usaha ekonomi kreatif yang selama ini berkembang di kota Malang.
Substansi masalahnya, kebijakan ini menentukan objek pajak berdasarkan omzet bukan laba bersih. Omzet Rp15 juta per bulan tidak menjamin pengusaha mendapatkan untung yang layak.
Di tengah lesunya ekonomi banyak juga pengusaha yang rela mengambil margin 15-20% agar bisnis bisa tetap berjalan. Apabila perhitungan kasar dengan omzet Rp15 juta mereka mendapatkan untung bersih hanya Rp3 juta.
Artinya jika mereka dibebankan pajak 10% dari omzet maka pemerintah secara sadar memungut 50% keuntungan pelaku usaha. Ini bukan hanya tentang layak atau tidak layak tetapi juga pemerintah dengan sadar telah menindas rakyatnya sendiri.
Pemerintah memberikan alasan bahwa kebijakan ini diterapkan agar dapat memperkuat APBD kota Malang. Dengan menarik pajak dari sektor yang belum tersentuh sebelumnya, harapannya pendapatan daerah bisa meningkat agar program-program pembangunan dan layanan publik bisa berjalan dengan baik. Pun pajak yang dikutip dari para pelaku UMKM sebagian akan dikeluarkan dalam bentuk bantuan sosial sehingga hal ini bisa berjalan dalam pemerataan kesejahteraan.
Akan tetapi, alih-alih pembangunan yang dicanangkan dapat meningkatkan kesejahteraan, kebijakan ini justru berpotensi memicu efek sebaliknya. Dengan adanya aturan ini UMKM akan tertekan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bahkan kebijakan ini juga bisa mendorong pengusaha untuk “bersembunyi”.
Pengusaha akan menyembunyikan omzet, membagi-bagi usahanya agar tetap kecil di atas kertas. Hal Ini adalah respon normatif akibat kebijakan yang dianggap memberatkan usaha mereka padahal justru hal tersebut adalah jalan mereka untuk tetap bertahan hidup.
Padahal di saat banyak negara mendorong inklusi ekonomi dengan membuka akses usaha kecil terhadap peluang pembiayaan, peningkatan kompetensi, peningkatan teknologi dan ekspansi pasar baru. Pemerintah kota Malang justru berjalan mundur dan kontraproduktif terhadap tujuan yang ingin dicapai.
UMKM ibarat tulang punggung ekonomi karena menyerap tenaga kerja lokal terbesar. Beban pajak yang besar bisa memaksa mereka untuk melakukan efisiensi seperti mengurangi pegawai, mengurangi waktu operasional atau menaikkan harga.
Jika akhirnya pengusaha menaikkan harga tentunya akan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dan tersendatnya sirkulasi ekonomi di kota Malang.
Efek lainnya adalah akibat beban pajak yang besar konsumen akan memilih alternatif produk yang lebih murah walaupun berasal dari luar kota. Ini juga bisa menurunkan daya saing usaha lokal dan uang warga malang justru keluar bukan bersirkulasi di dalam.
Usaha untuk meningkatkan PAD agar sebuah daerah bisa mandiri secara fiskal bukanlah hal yang salah. Tetapi jika ditempuh dengan membebani rakyat kecil apakah hal tersebut layak untuk dijalankan?
Sudah seharusnya pemerintah daerah bisa mencari ide yang lebih strategis. Pendapatan daerah bisa otomatis naik apabila ekonomi bisa bertumbuh secara sehat, optimalisasi pemungutan pajak korporasi besar seperti kendaraan mewah dan properti mewah.
Akan tetapi jika memang pemerintah sangat yakin untuk merangkul pelaku usaha melalui perpajakan, pemerintah bisa mengenakan pajak berbasis laba bersih bukan omzet. Itu akan lebih adil karena pada dasarnya setiap usaha walaupun jenis yang sama memiliki perhitungan ekonomi berbeda-beda. Akan sangat tidak etis mengutip pajak 10% kepada usaha yang hanya memiliki margin 20%.
Kebijakan yang membebani rakyat akan menambah apatisme masyarakat terhadap pemerintah. Jangan sampai mereka lebih senang pemerintah yang tidur saat bekerja daripada aktif bekerja namun hasil kerjanya justru merugikan masyarakat kecil.
***
*) Oleh : Fitria Nurma Sari, Dosen Perbankan Syariah Universitas Ahmad Dahlan.
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |