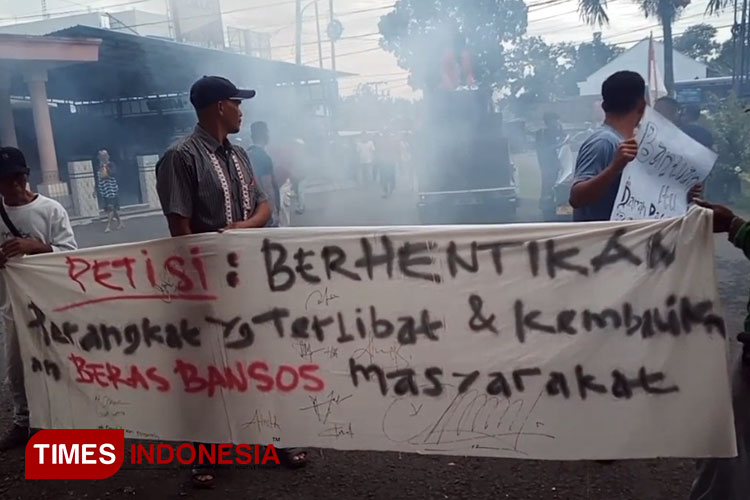TIMES MALANG, JAKARTA – Di Yunani kuno, ada sebuah tempat yang disebut Taman Akademia atau Park Academy. Ada pula yang menyebutnya sebagai Akademi Plato. Itu adalah sebuah lembaga pengajaran yang didirikan di taman atau hutan luar gerbang utara Kota Athena. Di sanalah Plato mengajar murid-muridnya tentang ide-ide besar, tentang keadilan, tentang negara yang baik.
Akademia adalah tempat bagi pikiran yang bebas, bagi filsuf yang merenungkan dunia tanpa beban kepentingan praktis. Tapi bayangkan jika Plato tiba-tiba berhenti mengajar, mengenakan helm dan rompi tambang, lalu membawa serta murid-muridnya turun ke perut bumi menggali mineral. Akademia pun berubah, bukan lagi tempat berpikir, tapi tempat mengeksploitasi.
Indonesia kini menghadapi sesuatu yang baru. Sebuah pasal dalam revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) memberikan perguruan tinggi, taman akademia kita, hak untuk memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).
Universitas yang selama ini menjadi ruang pengetahuan, kini bisa menjadi pemilik lahan tambang. Dari laboratorium dan ruang diskusi, mahasiswa dan dosen atau sesiapapun di lingkungan akademia bisa terlibat langsung dalam industri ekstraktif.
Di satu sisi, ini terdengar sebagai ide cemerlang. Universitas bisa langsung terlibat dalam dunia nyata, tak hanya menjadi pengamat dari kejauhan. Tambang bukan lagi sekadar objek penelitian, tetapi menjadi bagian dari ekosistem akademik itu sendiri. Fakultas teknik pertambangan, geologi, dan lingkungan bisa mengembangkan riset berbasis praktik, bukan sekadar teori di atas kertas atau dalam diktat.
Di negara-negara lain, model semacam ini sudah diterapkan. Di Kanada dan Australia, beberapa universitas memiliki tambang riset. Namun, ada perbedaan signifikan. Tambang yang mereka kelola biasanya berskala kecil, digunakan untuk eksperimen, bukan untuk produksi massif. Sementara dalam versi Indonesia, potensi bisnisnya jauh lebih luas.
Dan di sini letak masalahnya: universitas bukanlah perusahaan.
Universitas, dalam bentuk idealnya, adalah ruang kebebasan akademik. Ia bertugas mencari kebenaran, bukan mencari keuntungan. Jika universitas memiliki tambang, bisakah ia tetap menjaga independensinya?
Mari kita bayangkan sebuah skenario. Seorang profesor geologi di sebuah universitas menulis jurnal yang mengkritik praktik pertambangan karena merusak lingkungan. Tapi di saat yang sama, universitasnya sendiri memiliki tambang yang berkontribusi pada deforestasi dan pencemaran air. Apakah profesor itu akan tetap bebas mengungkapkan kritiknya?
Atau skenario lain. Sebuah universitas mendapatkan dana besar dari hasil tambangnya. Lalu ada penelitian yang menunjukkan bahwa pertambangan di daerah tersebut merugikan masyarakat adat. Apakah universitas akan tetap mendukung penelitian semacam itu, ataukah ia akan memilih diam demi menjaga kepentingan bisnisnya?
Konflik kepentingan ini berbahaya. Universitas bisa kehilangan identitasnya sebagai institusi pencari ilmu dan berubah menjadi korporasi yang lebih peduli pada laba daripada kebenaran.
Di mitologi Yunani, ada kisah Raja Midas. Ia diberi anugerah oleh dewa Dionysus: segala yang disentuhnya berubah menjadi emas. Awalnya, ia sangat bahagia. Tapi kemudian menyadari bahwa makanan yang disentuhnya juga berubah menjadi emas. Ia tidak bisa makan, tidak bisa minum. Akhirnya, ia terperangkap dalam kutukan dari anugerah yang didambakannya.
Universitas yang mendapat izin tambang bisa jadi seperti Raja Midas. Pada awalnya, keuntungan dari sektor ini bisa menjadi berkah: dana penelitian meningkat, beasiswa bertambah, fasilitas akademik membaik. Tapi jika tidak berhati-hati, mereka bisa kehilangan sesuatu yang lebih berharga: Integritas intelektual.
Ketika universitas mulai mengejar keuntungan, apakah masih ada jaminan bahwa mereka tetap menjadi tempat bagi kebebasan berpikir? Apakah mereka masih bisa jujur dalam menilai dampak pertambangan terhadap lingkungan dan masyarakat?
RUU Minerba yang membuka peluang bagi perguruan tinggi untuk memiliki izin tambang ini adalah gagasan yang ambisius. Ia menawarkan kesempatan bagi dunia akademik untuk lebih dekat dengan dunia industri. Namun, batas antara ilmu dan bisnis terlalu tipis untuk diabaikan.
Jika kebijakan ini diterapkan, transparansi dan pengawasan menjadi mutlak. Ada beberapa hal yang harus dipastikan:
Universitas tidak boleh beroperasi seperti perusahaan tambang biasa. Jika mereka diberikan izin, maka harus ada batasan ketat: tambang yang dikelola sedapat mungkin bersifat riset dan bukan komersial skala besar atau bisa disiasati dengan menjadi sub-kontraktor sebuah perusahaan pertambangan nasional.
Harus ada pula pemisahan yang jelas antara kepentingan akademik dan kepentingan bisnis. Jangan sampai fakultas kehilangan independensinya hanya karena universitas terlibat dalam eksploitasi sumber daya alam.
Kemudian, dampak sosial dan lingkungan harus menjadi perhatian utama. Jika universitas benar-benar ingin terlibat dalam pertambangan, mereka harus menunjukkan standar yang lebih tinggi dari perusahaan biasa. Mereka harus menjadi model dalam pertambangan yang bertanggung jawab.
Sejarah menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan eksploitasi sumber daya alam sering kali berada dalam hubungan yang rumit. Di satu sisi, ilmu memungkinkan kita memahami dan mengelola sumber daya dengan lebih baik. Di sisi lain, ada godaan untuk menggunakan ilmu itu demi keuntungan jangka pendek, mengorbankan prinsip yang lebih besar.
Taman Akademia dulu adalah tempat filsafat berkembang, tempat orang-orang bertanya tentang hakikat keadilan dan kebaikan. Jika hari ini Akademia mulai menggali perut bumi, pertanyaannya adalah: apakah mereka masih mencari kebenaran, ataukah hanya mencari emas seperti Raja Midas?
***
*) Oleh : Jafar G Bua, Mantan Produser Lapangan CNN Indonesia, Kini Tenaga Ahli Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI.
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
| Pewarta | : Hainorrahman |
| Editor | : Hainorrahman |