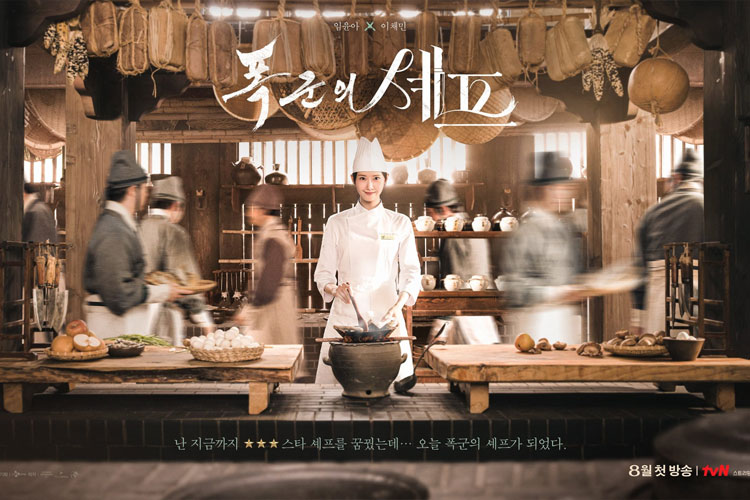TIMES MALANG, MALANG – Tepat tanggal 1 Agustus 2025, rakyat diberikan kado istimewa oleh presiden RI dengan memberikan abolisi kepada Tom Lembong, yang telah divonis bersalah dalam kasus impor beras selama dia menjabat sebagai menteri perdagangan.
Keputusan Presiden untuk memberikan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, mantan pejabat tinggi ekonomi nasional yang telah divonis bersalah dan berkekuatan hukum tetap (inkrah), menimbulkan tanda tanya besar.
Apakah ini sekadar bentuk hak prerogatif Presiden yang konstitusional, atau telah menjadi jalan pintas politik yang mencederai etika hukum dan prinsip keadilan?
Pertanyaan itu wajar mengemuka di ruang publik. Sebab, abolisi yang seharusnya merupakan instrumen hukum dalam konteks tertentu dan terbatas, kini justru dipertanyakan keberpihakannya, apakah untuk kemaslahatan umum, atau untuk kepentingan segelintir elite?
Abolisi dalam Perspektif Konstitusi dan Hukum Positif
Pakar Hukum Tata Negara Prof. Denny Indrayana (2020) pernah menyatakan: "Kewenangan presiden dalam memberi abolisi bukanlah kekuasaan absolut. Ia tetap harus tunduk pada asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik."
Secara konstitusional, Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 menegaskan: "Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR."
Artinya, Presiden memang memiliki kewenangan hukum untuk mengeluarkan abolisi terhadap seseorang yang sedang atau telah menjalani proses pidana, sepanjang DPR memberikan pertimbangan dan persetujuan. Hal ini juga ditegaskan dalam UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi.
Namun, penting dicatat bahwa abolisi berbeda dengan grasi. Grasi diberikan kepada terpidana, dan bertujuan untuk meringankan atau menghapuskan hukuman. Sementara abolisi adalah penghentian penuntutan pidana, baik sebelum atau sesudah adanya vonis.
Dalam kasus Tom Lembong, abolisi diberikan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Maka, secara substantif, langkah tersebut tidak hanya menghentikan proses hukum, tetapi berimplikasi pada penghapusan pertanggungjawaban pidana secara total.
Menyoal Kepantasan Etis dan Moral dalam Pemberian Abolisi
Prof. Saldi Isra, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, menekankan bahwa pemberian abolisi atau grasi yang tidak melalui pertimbangan moral dan kemaslahatan umum berisiko menjadi bentuk impunitas terselubung.
Secara hukum positif, Presiden berhak memberi abolisi. Namun dalam politik hukum Indonesia, segala tindakan hukum haruslah dijalankan dengan asas kepatutan, keadilan, dan proporsionalitas.
Di sinilah problem muncul, apakah penghapusan pertanggungjawaban pidana untuk seorang elite politik atau pejabat tinggi seperti Tom Lembong menunjukkan keberpihakan negara pada keadilan substantif, atau sekadar kompromi politis?
Jika kita menengok sejarah, abolisi biasanya digunakan dalam konteks rekonsiliasi nasional, pertimbangan kemanusiaan, atau menghindari konflik horizontal.
Misalnya, abolisi pernah diberikan dalam konteks Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pasca-MoU Helsinki. Namun dalam kasus ini, alasan politis dan strategis tidak tampak dominan.
Publik tentu bertanya: Di mana letak urgensi nasionalnya? Apakah abolisi diberikan karena ada pertimbangan kemanusiaan atau karena aktor yang bersangkutan memiliki posisi penting dalam konfigurasi kekuasaan saat ini?
Krisis Etika Politik Hukum
Kasus ini patut dikhawatirkan menjadi preseden buruk dalam praktik politik hukum Indonesia. Tindakan mengintervensi proses pidana, apalagi setelah ada vonis pengadilan, bisa menciptakan persepsi publik bahwa hukum hanya berlaku untuk rakyat kecil, dan tidak menyentuh mereka yang dekat dengan kekuasaan.
Padahal, dalam prinsip rule of law, pengadilan harus dijaga marwah dan independensinya. Ketika kekuasaan eksekutif bisa membatalkan proses hukum melalui abolisi yang tidak disertai urgensi yang cukup, maka fungsi yudikatif mengalami delegitimasi secara moral dan institusional.
Kita bisa menyebut ini sebagai bentuk “soft impunity” bentuk pengampunan negara terhadap elite, bukan karena mereka tidak bersalah, melainkan karena memiliki kedekatan kekuasaan. Ini bukan hanya persoalan legalitas, tetapi persoalan etik dan akuntabilitas moral kekuasaan.
Evaluasi Kritis terhadap Politik Hukum Indonesia
Kasus ini seharusnya menjadi momentum evaluasi besar-besaran terhadap arah politik hukum nasional. Kita harus kembali menempatkan hukum sebagai alat rekayasa sosial, bukan alat legitimasi politik.
Beberapa catatan penting yang perlu dikedepankan: Pertama, penggunaan hak prerogatif Presiden dalam bidang hukum harus diawasi secara kritis oleh DPR dan masyarakat sipil. Jangan sampai menjadi instrumen perlindungan elite.
Kedua, dibutuhkan regulasi turunan yang lebih ketat dalam hal pemberian abolisi, termasuk batasan situasi, kategori tindak pidana, serta syarat transparansi publik.
Ketiga, partisipasi publik harus dijamin dalam pemberian abolisi dan amnesti. Saat ini, prosesnya terlalu tertutup dan tanpa mekanisme keberatan dari masyarakat.
Dalam laporan ICW (Indonesia Corruption Watch, 2023), disebutkan bahwa dari 120 lebih kasus korupsi elite yang diajukan ke pengadilan dalam satu dekade terakhir, sebagian besar berakhir pada vonis ringan atau lepas karena celah hukum dan tekanan politik.
Namun, tidak satu pun dari mereka yang mendapat abolisi secara terang-terangan seperti ini. Bahkan dalam kasus Baiq Nuril, seorang guru korban pelecehan seksual, Presiden Jokowi memilih memberikan amnesti, setelah melalui proses panjang, tekanan publik, dan pertimbangan kemanusiaan.
Jika Baiq Nuril saja harus menunggu dan berjuang, mengapa seorang elite sekelas Tom Lembong bisa langsung dibebaskan melalui abolisi?
Antara Jalan Pintas Politik dan Masa Depan Etika Hukum
Kasus abolisi Tom Lembong menghadirkan dilema, secara hukum sah, tapi secara etik menuai persoalan. Ini bukan hanya soal satu orang atau satu kasus, tetapi soal arah masa depan keadilan hukum kita.
Jika abolisi bisa diberikan dengan mudah tanpa urgensi dan argumentasi publik yang meyakinkan, maka rakyat akan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga hukum. Dan ketika kepercayaan hilang, maka yang tersisa dari hukum hanyalah simbol, bukan substansi.
Politik Hukum, Antara Legalitas dan Keadilan
Politik hukum Indonesia dalam kasus ini terlihat sedang bergeser: dari orientasi pada keadilan sosial, menuju akomodasi terhadap kekuasaan dan elite. Hal ini mempertegas kecenderungan instrumentalisasi hukum, di mana hukum digunakan sebagai alat untuk melindungi kekuasaan, bukan menegakkan kebenaran.
Padahal, dalam doktrin negara hukum (rechtstaat), prinsip “equality before the law” adalah harga mati. Siapa pun elite atau rakyat kecil harus berada dalam posisi yang setara di depan hukum.
Kita tidak sedang mempertanyakan wewenang Presiden, tetapi kita sedang mempertanyakan: Apakah kekuasaan itu masih dijalankan untuk rakyat, atau hanya untuk lingkaran kuasa?
***
*) Oleh : Husnul Hakim, SY., MH., Dekan FISIP UNIRA Malang dan Pemerhati Hukum dan Politik.
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |