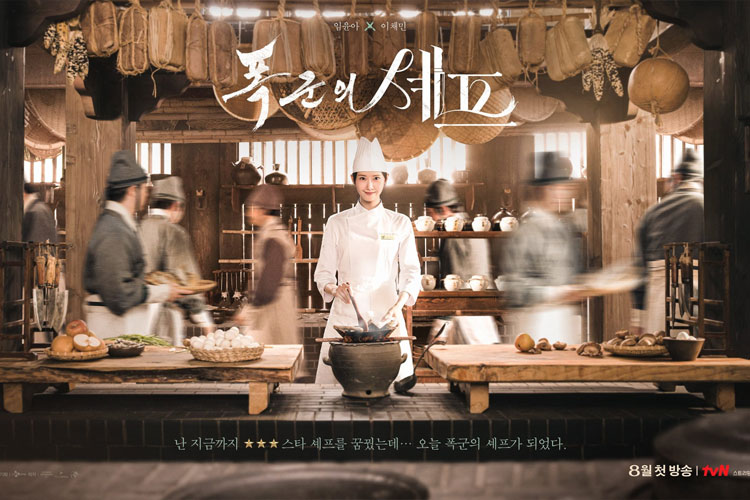TIMES MALANG, MALANG – Menjelang peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ruang publik kita dihebohkan oleh fenomena yang tak disangka: bendera bajak laut dari anime One Piece berkibar di berbagai sudut negeri.
Simbol Jolly Roger dengan topi jerami itu tak lagi hanya milik penggemar, tapi hadir di truk-truk jalanan, motor pelajar, hingga depan rumah warga.
Sebuah ekspresi budaya pop yang, di mata sebagian orang, hanyalah hiburan. Namun bagi yang lebih jeli membaca zaman, ini adalah pertanda sosial yang mengganggu peta lama tentang nasionalisme.
Ketika Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut fenomena ini sebagai potensi “gerakan sistematis memecah belah bangsa”, dan pemerintah mengingatkan potensi pelanggaran UU No. 24 Tahun 2009, suara protes dari masyarakat justru semakin menguat.
Kita dihadapkan pada pertanyaan yang jauh lebih fundamental: mengapa sebuah bendera fiksi bisa begitu merasuk ke hati publik, hingga terasa lebih “mewakili” ketimbang simbol resmi negara?
Bahasa Diam Generasi yang Tak Didengar
Dalam ilmu budaya, simbol tak pernah netral. Ia adalah bahasa yang memuat ingatan kolektif, aspirasi, sekaligus luka sosial. Jolly Roger di dunia One Piece bukan sekadar lambang bajak laut, tapi representasi kebebasan, solidaritas, dan perlawanan terhadap ketidakadilan.
Monkey D. Luffy dan kawan-kawan adalah simbol heroisme yang sederhana, jujur, dan berpihak kepada yang tertindas nilai-nilai yang, ironisnya, semakin langka kita temui dalam narasi kepemimpinan di dunia nyata.
“Ini bukan soal suka anime atau tidak,” kata Riko Noviantoro, pengamat budaya populer. “Ini adalah simbol kritik publik yang halus, sebuah protes yang berbicara tanpa berteriak. Karena ruang ekspresi resmi terlalu sempit, maka simbol fiksi diangkat menjadi bahasa perlawanan.”
Pengibaran bendera One Piece mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap simbol negara yang dianggap hampa makna. Di tengah perayaan kemerdekaan yang seharusnya menjadi pesta persatuan, banyak rakyat justru merasa menjadi penonton.
Mereka menyaksikan harga kebutuhan pokok melambung, kesenjangan sosial menganga, pengangguran merajalela, dan elite politik sibuk menjaga citra sembari melupakan esensi.
Di ruang kosong inilah Topi Jerami hadir sebagai identitas baru. Ia bukan hanya lambang bajak laut fiksi, tapi menjadi simbol keterhubungan dan harapan bagi mereka yang lelah dikhianati janji-janji lima tahunan.
Maka tak heran, sopir truk, pelajar, mahasiswa, hingga pedagang kaki lima merasa lebih terwakili oleh semangat kru Topi Jerami daripada oleh pidato resmi yang kian kehilangan daya magisnya.
Tentu negara wajib menjaga kehormatan simbol resminya. Tapi ketika reaksi terhadap ekspresi kultural justru cenderung represif dan paranoid, itu hanya akan memperdalam jurang komunikasi antara negara dan rakyat.
Simbol-simbol pop culture, sebagaimana dikatakan Stuart Hall, adalah bagian dari produksi makna dalam masyarakat. Ketika rakyat mulai memilih simbol fiksi sebagai bahasa protes, itu bukan karena mereka tidak menghargai Merah Putih, melainkan karena mereka merasa Merah Putih tidak lagi “mendengarkan”.
Narasi kemerdekaan selama ini terlalu fokus pada seremoni dan atribut. Kita sibuk mengatur posisi bendera di tiang, namun abai memastikan nilai-nilai yang dikandungnya keadilan, keberanian, dan pengorbanan benar-benar hadir di tengah rakyat. Nasionalisme menjadi ritual kosong ketika rakyat harus mengibarkan bendera negara di tengah kemiskinan yang membelenggu.
Delapan dekade setelah proklamasi, pertanyaan mendasar itu kembali menggema: apakah kemerdekaan hanya sebatas perayaan simbolik? Jika bendera nasional hanya muncul saat upacara, namun sehari-hari yang berkibar adalah simbol fiksi, bukankah ini sinyal bahwa kita sedang menghadapi krisis makna nasionalisme?
Bukan Tentang Luffy, Tapi Tentang Kita
Fenomena bendera One Piece bukan soal suka atau tidak suka dengan anime. Ini adalah refleksi sosial yang lebih dalam: rakyat kecil, khususnya generasi muda, sedang mencari ruang untuk bicara. Mereka tidak menemukan harapan dalam jargon politik, maka mereka menciptakan simbol-simbol baru yang dirasa lebih jujur.
Pertanyaannya, apakah negara berani mendengarkan? Ataukah negara akan memilih meredam simbol, tanpa peduli pada suara yang sebenarnya sedang berteriak di balik diamnya? Protes simbolik semacam ini adalah peringatan dini bahwa ada sesuatu yang sangat salah dalam hubungan antara negara dan warganya.
Mengecam bendera fiksi tanpa mengoreksi luka sosial yang melahirkannya adalah cara berpikir yang terlalu dangkal. Bendera One Piece hanyalah gejala. Yang lebih penting adalah penyakit sosial yang ia wakili: rasa kehilangan, keterputusan, dan ketidakpercayaan.
Maka, sebelum kita sibuk mencabut bendera Topi Jerami dari jalanan, mari kita renungkan: apakah Merah Putih sudah benar-benar kita rawat di hati rakyat, ataukah ia sekadar berkibar di udara kosong seremoni? Karena seringkali, suara yang paling keras datang dari simbol yang paling sunyi.
***
*) Oleh : Thaifur Rasyid, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang.
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |