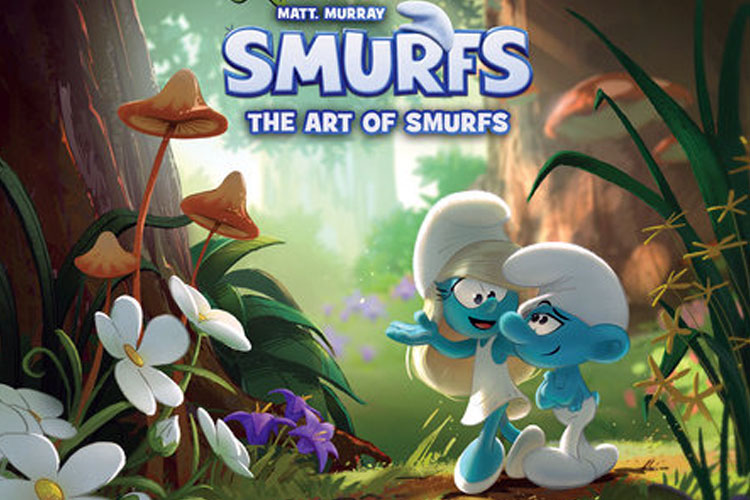TIMES MALANG, JAKARTA – Sejak didirikan pada tahun 1947, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) membawa misi besar perkaderan: membina kader pemimpin (harapan) umat dan bangsa. Namun dalam praktiknya, proses kaderisasi HMI tidak jarang terjebak dalam pola reproduksi struktur kekuasaan internal.
Orientasi kaderisasi lebih banyak terarah untuk mempertahankan struktur dominasi organisasi daripada mendorong perubahan sosial yang kritis. Fenomena ini menunjukkan bagaimana organisasi mahasiswa yang semula berwatak transformatif, berubah menjadi institusi semi-formal yang lebih sibuk melanggengkan masalah dirinya sendiri.
Dalam perspektif filsafat sosial kritis, khususnya pemikiran Pierre Bourdieu (1977), pola ini dapat dibaca sebagai mekanisme reproduksi simbolik. Struktur kekuasaan dalam organisasi direproduksi melalui habitus kaderisasi, di mana para ‘elite lama’ mencetak kader-kader baru yang mengikuti pola dan nilai mereka.
Proses ini tidak memungkinkan adanya ruang yang sehat bagi pemikiran alternatif atau sikap kritis. Kaderisasi pun berubah menjadi ajang penyesuaian yang dogmatis, bukan pengubahan paradigma kritis.
Akibatnya, proses ini menjauhkan lahirnya pemimpin-pemimpin transformatif, melainkan administrator yang kompatibel dengan kultur/sistem lama. Herbert Marcuse (1964) menyebut fenomena ini sebagai manusia berdimensi tunggal (one-dimensional man), yakni individu yang kehilangan kapasitas berpikir mandiri dan kritis karena telah terserap ke dalam logika sistem yang membelenggu namun tampak wajar/normal.
HMI pun secara perlahan kehilangan watak intelektual-kritisnya, dan semakin dekat menjadi ‘lembaga-teknokratis’ yang lebih banyak melahirkan politisi murni, bukan pembebas sosial.
Di titik ini, menjadi penting untuk merefleksikan ulang secara radikal: apakah kaderisasi di HMI masih menjadi medan pendidikan kesadaran ataukah justru menjadi alat ‘domestikasi’ generasi muda Islam? Jika kaderisasi tidak ditransformasikan, maka HMI akan terus menjadi pabrik kader struktural—bukan kader ideologis yang mampu membaca zaman dan melampauinya.
Tantangan Krisis Kepemimpinan
Krisis kepemimpinan yang dialami bangsa ini tak terlepas dari krisis epistemologis dalam kaderisasi organisasi seperti HMI. Dan krisis kepemimpinan di HMI hari ini tidak bisa dilepaskan dari dominasi rasionalitas-instrumental dalam proses pengaderannya.
Kader didorong untuk menguasai teknik-teknik berorganisasi, membangun jaringan pragmatis, dan memenangkan posisi struktural. Rasionalitas seperti ini cenderung meminggirkan orientasi etik dan ideologis dari proses kepemimpinan itu sendiri (Habermas, 1984). Sehingga yang muncul adalah kader yang mahir dalam manuver taktis, namun kering dalam hal kepekaan sosial.
Dalam logika rasionalitas-instrumental, keberhasilan kaderisasi diukur dari seberapa cepat seorang kader menapaki tangga struktural. Kepemimpinan didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan mengelola organisasi, bukan kapasitas untuk meretas struktur ketidakadilan.
Hasilnya adalah pemimpin-pemimpin yang cakap secara teknis namun nihil imajinasi transformatif. Mereka justru menjadi bagian dari problem sosial, bukan pemecahnya.
Lebih lanjut, hubungan kader dengan organisasi pun cenderung menjadi bersifat transaksional. Kader melihat organisasi sebagai jalan untuk mendapatkan legitimasi, bukan sebagai ruang pembentukan diri dalam perjuangan.
Situasi ini memperkuat sikap apatis, konformis, dan oportunis. HMI pun berubah dari gerakan ide menjadi wadah yang diperebutkan oleh mereka yang bercita-cita jabatan.
Untuk keluar dari krisis ini, perlu dilakukan reorientasi dalam tubuh HMI. Rasionalitas-instrumental harus ditandingi oleh rasionalitas-komunikatif, di mana kepemimpinan lahir dari proses diskursif, etis, dan dialogis dalam ruang publik (Habermas, 1984). Sehingga seorang pemimpin tidak lagi diukur dari daya manajerialnya semata, tetapi dari daya kritis dan keberpihakannya terhadap masyarakat yang tertindas.
Perkaderan Emansipatoris dan Transformatif
Dalam konteks pembaruan kaderisasi HMI, pemikiran Paulo Freire menjadi sangat relevan. Pendidikan kader harus menjadi proses pedagog kritis, bukan indoktrinasi struktural (Freire, 1970). Kaderisasi tidak boleh hanya mentransfer pengetahuan dan strategi organisasi, tetapi harus membangkitkan kesadaran reflektif yang mampu membongkar realitas penindasan dan membuka kemungkinan emansipasi sosial.
Kepemimpinan yang dibentuk melalui pendekatan ini adalah kepemimpinan transformatif-bukan hanya administratif. Pemimpin transformatif lahir dari proses kesadaran, bukan sebatas dari kompetisi/kalkulasi strategi.
Mereka tidak sekadar mampu mengelola program kerja, tetapi juga memiliki sensitivitas terhadap ketimpangan sosial dan keberanian untuk menggugat kebobrokan sistem yang destruktif. Ini mengandaikan ruang kaderisasi yang terbuka, egaliter, dan memberi tempat pada kritik maupun auto-kritik sebagai bagian dari dinamika pertumbuhan organisasi dan sosial.
Antonio Gramsci (1971) menyebut peran semacam ini sebagai tugas intelektual organik-yaitu mereka yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga menyatu dengan perjuangan rakyat dan mampu mengartikulasikan arah perubahan sosial.
HMI semestinya menjadi rahim lahirnya intelektual-intelektual organik tersebut, bukan sekadar teknokrat-birokratis. Artikulasi visi kebangsaan, keislaman, dan keadilan sosial tidak boleh berhenti pada wacana atau sebatas jargon yang diulang-ulang, melainkan harus diterjemahkan dalam praksis kaderisasi yang membebaskan.
Dalam kerangka inilah, kaderisasi HMI perlu didesain ulang sebagai proses emansipatoris: membentuk pemimpin yang bukan hanya cerdas, tetapi juga merdeka; bukan hanya terampil, tetapi juga berpihak pada kebenaran.
HMI mesti kembali ke akar historisnya sebagai gerakan intelektual yang berani melawan kesewenang-wenangan kekuasaan dan terdepan menjadi agen katalisator perubahan.
Kaderisasi emansipatoris juga harus memberi ruang bagi narasi alternatif yang terpinggirkan, termasuk suara kaum perempuan, kelompok minoritas, dan suara-suara kritis yang selama ini dianggap mengganggu stabilitas organisasi dan sosial.
Dalam kerangka ini, kepemimpinan tidak lagi dipahami sebagai dominasi, melainkan pelayanan/pengabdian dan pembebasan yang bersetia pada cita-cita luhur kehidupan. Kepemimpinan yang lahir dari proses ini akan lebih mampu menangkap kompleksitas zaman dan menjawab tantangan-tantangan sosial dengan keteguhan moral dan visi keadilan.
Hingga pada hematnya, HMI sebagai organisasi mahasiswa Islam terbesar harus berani melampaui romantisme sejarah. Ia harus menafsirkan ulang dirinya dalam konteks kontemporer, di mana tantangan kemiskinan struktural, krisis lingkungan, oligarki, dan eksklusi sosial serta persoalan lainnya semakin meresahkan.
Kaderisasi HMI harus menjadi jembatan antara idealisme nilai-nilai Islam dan praksis pembebasan. Di sinilah pentingnya mengintegrasikan etika profetik ke dalam sistem kaderisasi-yakni etika yang berpihak kepada yang lemah, melawan penindasan, dan membawa harapan emansipasi sosial demi membangun Indonesia dengan kepemimpinan yang lebih baik di masa depan. (*)
***
*) Oleh : Tubagus Damanhuri, Instruktur HMI.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |