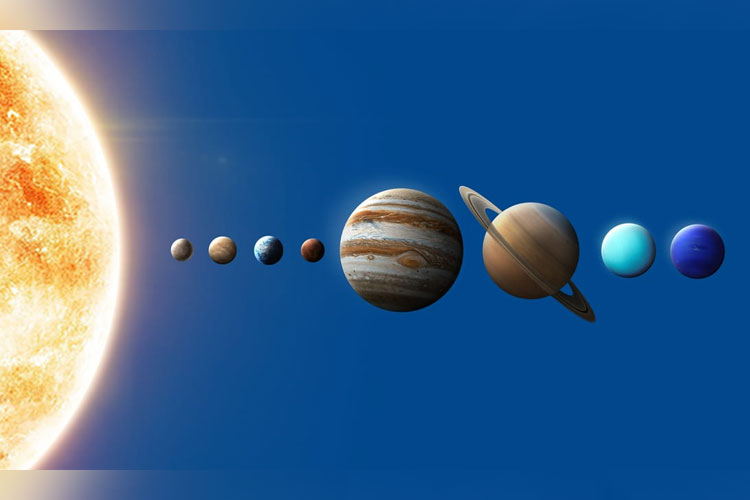TIMES MALANG, TANGERANG – Beberapa bulan lalu, bangsa Indonesia telah menyelenggarakan Pilkada serentak di berbagai daerah. Hal ini merupakan wujud nyata demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah sesuai Pasal 18 UUD 1945.
Melalui Pilkada, masyarakat dapat secara langsung memilih pemimpin daerah yang akan mengelola sumber daya lokal, termasuk sumber daya alam, manusia, dan potensi ekonomi. Semua itu bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di setiap daerah.
Namun, pelaksanaan Pilkada tidaklah berjalan mulus. Pasca pengumuman penetapan hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), situs resmi Mahkamah Konstitusi mencatat angka 1.136 perkara sengketa hasil Pilkada yang masuk dari berbagai daerah di Indonesia.
Mengenai hasil pemilihan, mulai dari money politics, kecurangan memanipulasi suara Daftar Pemilih Tetap (DPT), hingga dugaan keterlibatan aparatur negara yang seharusnya bersikap netral, mewarnai proses berjalannya Pilkada.
Untuk itu, sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 24C UUD 1945, mengamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yudikatif yang berwenang dalam menyelesaikan perselisihan hasil tersebut.
Jika kita menilik kembali Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dengan berfokus pada ketentuan yang ada pada peraturan, memang menunjukkan batasan yang jelas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani sengketa pemilu.
Frasa "tentang hasil pemilihan" mengindikasikan bahwa fokus utama MK dalam pengambilan keputusan sengketa pemilihan adalah pada aspek perhitungan suara yang mempengaruhi hasil akhir pemilihan. Artinya, MK tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengadili pelanggaran yang bersifat prosedural atau administratif selama proses pemilihan berlangsung.
Dan Pelanggaran prosedural dalam pemilihan sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 (UU Pemilu ) menjadi tanggung jawab dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sesuai Pasal 461 (1) dan Pasal 463 Bawaslu diberi kewenangan untuk memutus perkara pelanggaran dalam jangka waktu maksimal 14 hari.
Hal ini menjadi problematik, karena ketika penentuan putusan sengketa hasil pemilu lebih berfokus pada hasil akhir ketimbang melihat keseluruhan tahapan pemilihan, maka hal ini dapat mengaburkan esensi keadilan yang seharusnya menjadi tujuan utama lembaga peradilan.
Untuk itu, pendekatan positivisme yang cenderung kaku dan terpaku pada aspek prosedural ini memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi kompleksitas permasalahan pemilu.
Terlebih lagi, batasan waktu 14 hari yang diberikan oleh Bawaslu untuk memutus perkara dugaan sengketa kecurangan terasa sangat singkat, mengingat luasnya cakupan yang harus didalami dan membutuhkan investigasi mendalam pada penelusuran bukti yang tidak sederhana.
Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana Mahkamah Konstitusi (MK) mampu menghasilkan putusan yang benar-benar substantif jika hanya berpatokan pada hasil akhir saja?
Oleh karena itu, untuk menemukan esensi keadilan yang sebenarnya, rasanya tidak mungkin jika Mahkamah Konstitusi (MK) terus berada pada koridor peraturan tertulis,terlebih lagi putusan sengketa ini memiliki dampak langsung pada dinamika pemerintahan daerah yang bersengketa. Maka, MK harus berani mengambil suatu konsep putusan yang tidak sepenuhnya tertulis pada peraturan UUD 1945, yaitu dengan menggunakan pendekatan judicial activism.
Dengan menggunakan pendekatan ini, potensi menemukan keadilan substantif pada pengambilan keputusan akan lebih memungkinkan, karena pendekatan ini melihat hukum sebagai bentuk yang harus digali dan tidak memposisikan hakim hanya sebagai corong berlakunya peraturan. Konsekuensi nya, pertimbangan hakim dalam memutus perkara akan semakin kompleks.
Sebagai kelanjutan dari konsep tersebut, perlu ditekankan bahwa peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani perselisihan hasil pemilihan tidak dapat dibatasi hanya pada aspek hasil suara semata. MK harus juga mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi integritas proses pemilihan.
Dalam konteks ini, doktrin judicial activism memberikan landasan teoritis yang kuat bagi MK untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap proses elektoral secara keseluruhan. Lebih lagi, dalam urusan pemilihan yang merupakan proses konstitusi, hal ini semakin tepat karena judicial activism dalam kedudukannya dipandang sebagai benteng terakhir untuk melindungi supremasi konstitusi (Ni Luh, 2024).
Dengan demikian, MK tidak hanya berperan sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai guardian of constitution dalam menjamin terwujudnya demokrasi yang memiliki nilai konstitusional dan bukan hanya terpaku pada pelaksanaan formal.
***
*) Oleh : Muhammad Jundi Fathi Rizky, Mahasiswa Aktif Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah dan Peneliti di Distrik HTN Institute.
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
| Pewarta | : Hainorrahman |
| Editor | : Hainorrahman |