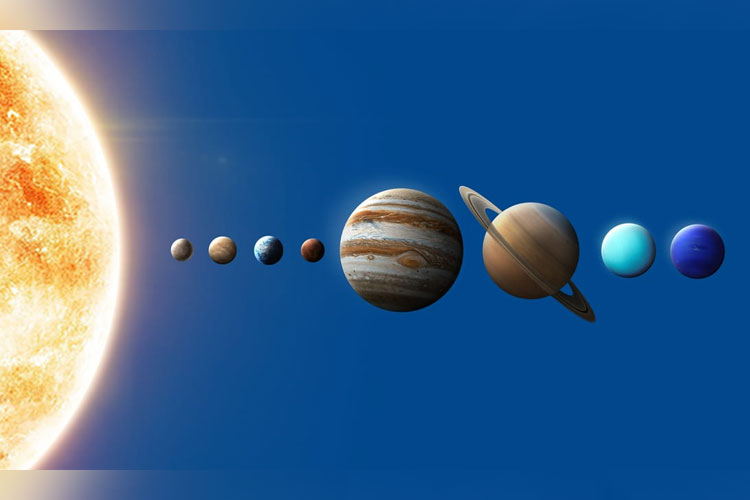TIMES MALANG, TANGERANG – Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menghembuskan angin segar bagi penguatan demokrasi yang konstitusional. Melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, MK memecah kebuntuan dominasi konfigurasi politik yang cenderung elitis, di mana pencalonan presiden dan wakil presiden terjerat dengan ambang-ambang batas minimal yang tidak rasional dan tidak konstitusional.
Akhirnya, MK menyatakan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. Pasal itu mengatur tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang mengharuskan diusung parpol atau gabungan parpol dengan 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional.
MK tidak hanya membatalkan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, melainkan juga mengembalikan hak konstitusional warga negara dan hak politik setiap partai politik peserta pemilu.
Ada tiga alasan pokok dan mendasar kenapa MK bergeser dari pendiriannya menyangkut konstitusionalitas ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.
Pertama, sebagai konsekuensi dari atribusi konstitusional senagaimana tertuang pada Pasal 6 ayat (1) UUD NRI 1945, dimana presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat yang memungkinkan setiap aspirasi politik pencalonan tersalurkan lewat partai politik yang tersedia.
Kedua, pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik merupakan hak konstitusional setiap partai politik peserta Pemilu. Dalam konteks itu, perolehan suara sebagai dasar penentuan persentase hak partai politik untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan bentuk ketidakadilan.
Ketiga, ambang batas minimal pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) berdasarkan perolehan suara atau kursi DPR sejatinya memaksakan logika sistem parlementer dalam praktik sistem presidensial.
Dalam sistem presidensial, lembaga legislatif dan eksekutif terpisah karena secara alamiah mendapatkan mandat secara berbeda. Atas dasar logika pemilihan langsung, constitusional right partai politik, dan logika presidensialisme, MK dengan tegas dan menyatakan ambang batas perolehan kursi 20% dan perolehan suara 25% adalah inkonstitusional secara mutlak.
Putusan tersebut tentu menggeser secara penuh pendirian MK menyangkut status norma ambang batas. Pasalnya, sebanyak 33 kali diuji, selama ini MK tetap dengan pendiriannya; ambang batas konstitusional dan merupakan kebijakan hukum terbuka. MK berhasil menepis mitos kekeramatan pasal ambang batas pencalonan yang selama ini hampir mustahil untuk dirobohkan.
Selama ini, terhadap kebijakan hukum terbuka (open legal policy), MK selalu konsisten menahan diri (judicial restraint). Dalam beberapa putusan, misalnya, MK mengualifikasi kebijakan hukum terbuka sebagai ranah pembuat undang-undang karena tidak disebutkan secara ekplisit dalam konstitusi. Sehingga tidak dijumpai parameter dalam UUD untuk menilai apakah suatu norma bertentangan atau tidak.
Tetapi belakangan, MK kerap melakukan yudisialisasi politik (judicialization of politics) dengan mengadili produk kebijakan hukum terbuka yang menyangkut kebijakan ambang batas (threshold). Misalnya Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menyatakan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4% inkonstitusional bersyarat sepanjang dirumusakan secara proporsional.
Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang menurunkan persentase ambang batas pencalonan kepala daerah menjadi 6,5%-10%, atau Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus secara kesuluruhan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold).
Dalam konteks ini, MK tampak melakukan judicial activism yang mengubah pendirian dari putusan-putusan sebelumnya. Meski dalam putusan 51-52-59/PUU-X/2012, MK memberikan batasan yang jelas adanya sikap yudisialisasi politik dapat diambil jika produk undang-undang (legal policy) jelas-jelas melangar rasionalitas, moralitas, dan merupakan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi (intolerable).
Ketika mengadili kosntitusionalitas kebijakan hukum terbuka, MK dihadapkan pada dua persaolan yang acap kali memuat antinomi tetapi tidak boleh saling menegasikan, yaitu persoalan substansi persoalan dalam menilai konstitusionalitas norma, dan persoalan kewenangan dalam memilih antara mengambil alih (judicial activism) atau menahan diri (judicial restraint).
Persoalan substansi merupakan persoalan yang dijawab MK apakah terdapat pelanggaran kosntitusional dari berlakunya suatu ketentuan. Dalam konteks ini, MK didorong untuk menjamin setiap hak konstitusional warga negara tidak dilanggar dengan berlakunya ketentuan undang-undang.
Sedangkan persoalan kewenangan, hal yang harus dijawab oleh MK apakah layak (appropriateness) suatu lembaga peradilan dan menguji suatu kebijakan yang merupakan ranah politik hukum undang-undang. Terkadang, persoalan substantif berkelindan dengan masalah kewenangan yang perlu dijawab secara bersamaan (Bisariyadi, 2015).
Kenyataannya pada perakara ambang batas pencalonan, MK memilih mengadili kebijakan hukum terbuka kendati diakui dalam puluhan putusan sebelumnya. Secara politik hukum, pergeseran tersebut sangat naif jika disebut hanya berdasarkan pada persoalan nalar rasionalitas, instrumen moralitas, atau adanya ketidakadilan.
Pasalnya, dalam putusan-putusan sebelumnya, pertimbangan tersebut telah dijawab dengan sistematis. Kecuali terdapat kebutuhan hukum baru yang menyangkut praktek-praktek bernegara belakangan.
Jika melihat konfigurasi politik belakangan, pasal-pasal yang dibatalkan konstitusionalnya oleh MK itu digunakan dalam kerja-kerja politik konspiratif yang tidak sehat, di mana pencalonan menjadi ajang transaksi politik dan praktik jegal menjegal antar partai politik.
Konfigurasi politik demikian mulai dipraktekkan menjelang perhelatan Pilkada 2024, di mana terdapat kecenderungan elit politik dalam membangun satu poros kekuatan besar yang meniadakan pilihan-pilihan alternatif. Konfigurasi semacam ini tidak hanya melanggar hak-hak warga negara, melainkan juga meracuni nalar demokrasi dan logika konstitusionalisme.
Pada tahap ini, sikap judicial activism menjadi suatu kebutuhan berhukum dan mendesak dilembagakan dalam kerja dan sistem peradilan ke depan. Lembaga peradilan (law institution) menjadi tumpuan penjagaan hak warga negara dari kerja politik yang tidak sehat jika lembaga parlemen (political institution) justru menjadi tumpul dan konspiratif dalam memanfaatkan ketentuan yang berlaku.
Dalam kerangka ini, lembaga peradilan menjadi harus untuk melakukan fungsi politik dan proses legislasi.
***
*) Oleh : Fahmi Aziz, S.H., Kepaniteraan Hukum Pengadilan Agama Tangerang.
*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainorrahman |
| Editor | : Hainorrahman |